Jangan Lupakan Pertanian Skala Kecil
Oleh: Khudori
PADA Oktober lalu, FAO menerbitkan buku The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in Family Farming. Buku itu mengulas peran penting pertanian keluarga.
Saya menyebut pertanian skala kecil karena 75 persen lebih dari mereka menguasai lahan kurang dari 1 hektar. Meskipun menguasai lahan gurem, mereka berperan amat penting dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan gizi. Mereka meningkatkan mata pencarian, mengelola sumber daya alam, melindungi lingkungan, dan mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya di pedesaan. Selama ini peran itu diabaikan.
Sampai saat ini 75 persen warga miskin adalah petani kecil. Porsi petani kecil di Asia 85 persen, di Indonesia 55 persen. Menggenjot investasi pada pertanian skala kecil tidak hanya memberi pangan dunia, tetapi juga menyelesaikan kemiskinan dan kelaparan.
Sekitar 500 juta dari 570 juta petani di dunia adalah petani skala kecil. Sekitar 70 persen kebutuhan makan lebih dari 7 miliar penduduk bumi saat ini disumbang oleh mereka (Lowder dkk, 2014). Sisanya diproduksi industri yang membentuk sistem rantai pangan. Bumi akan dilanda kelaparan akut tanpa pertanian skala kecil.
Hasil riset ekstensif menunjukkan pertanian keluarga/kecil jauh lebih produktif dari pertanian industrial sebab mengonsumsi sedikit energi, terutama apabila produksi pangan diperdagangkan di tingkat lokal/regional (Rosset, 1999).
Bukti-bukti menunjukkan pertanian skala kecil dan terdiversifikasi bisa beradaptasi dan pejal. Ini sekaligus model keberlanjutan yang lebih ramah dari kearifan lokal dan keragaman hayati. Sejak 1960-an, petani mengembangkan 1,9 juta varietas tanaman. Pada saat sama, industri pemulia tanaman hanya mengembangkan 72.500 varietas.
Pertanian skala kecil lebih ramah terhadap perubahan iklim (Altieri, 2008). Di banyak negara berkembang, tak terkecuali Indonesia, peran pertanian skala kecil mengalami peminggiran luar biasa. Sejak 1990-an, mengikuti saran Bank Dunia dan IMF, negara berkembang menyunat investasi pertanian, mempromosikan led-export production. Pertanian negara berkembang berubah radikal: dari terdiversifikasi dalam skala kecil-lokal menjadi model ekspor-industrial-monokultur yang digerakkan korporasi global. Petani pun merana, impor pangan meledak dan kelaparan meruyak.
Model pertanian ekspor industrial monokultur yang diklaim mujarab ternyata bukan resep ampuh mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Bagi International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), model pertanian ekspor industrial monokultur menghancurkan lingkungan (air dan tanah), mengerosi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal, serta mengekspos warga pada kerentanan tak terperi.
Krisis pangan terjadi akibat tali-temali suplai dan stok pangan menyusut, gagal panen, krisis BBM, perubahan iklim, konversi pangan ke biofuel, dan spekulasi. Namun, bagi IAASTD, akar terdalam krisis pangan karena pemerintah lupa mengurus pertanian skala kecil, aturan perdagangan tak adil, dan dumping negara maju.
Untuk mengikis kemiskinan, kelaparan, dan degradasi lingkungan, IAASTD menyarankan agar memperkuat pertanian skala kecil, meningkatkan investasi pertanian agroekologis, mengadopsi kerangka kerja perdagangan yang adil, menolak transgenik, memberi perhatian khusus pada kearifan lokal, memberi peluang sama (kepada warga) agar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membalik akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan modal) dari korporasi ke komunitas lokal, serta memperkuat organisasi tani, termasuk hak warga menentukan sendiri sistem (produksi, konsumsi, dan distribusi) pangan mereka, yang kesemua poin itu merupakan inti konsep kedaulatan pangan.
Di Indonesia, peran pertanian skala kecil luar biasa. Peran mereka bisa dihitung secara sederhana. Produksi padi pada 2013 sebesar 71,29 juta ton gabah. Jika dikalikan Rp 4.500/kg, nilainya Rp 320,8 triliun. Produksi jagung 18,5 juta ton. Apabila harganya Rp 4.000/kg, nilainya Rp 74 triliun. Produksi kedelai 0,78 juta ton dengan harga Rp 7.500/kg bernilai Rp 5,85 triliun. Produksi gula 1,78 juta ton dengan harga Rp 9.000/kg nilainya mencapai Rp 16 triliun. Hanya dari empat komoditas, jika usaha tani dianggap korporasi, omzetnya Rp 416,67 triliun. Apakah ada kekuatan korporasi di Indonesia sebesar itu? Hebatnya, mereka pakai modal sendiri, bahkan jika gagal panen, ditanggung sendiri.
Peran negara
Apa peran negara dalam membantu petani kecil? Boleh dikatakan minimal, kalau tidak disebut tak ada. Petani dibiarkan gurem. Akses terhadap lahan nyaris tertutup. Bendungan, irigasi, dan jalan desa rusak. Transportasi dan rantai pasok yang amburadul membuat produk pertanian tak terangkut. Kalaupun terangkut, harganya selangit dan tak mampu bersaing dengan produk serupa dari luar negeri. Petani dan pertanian dicap tidak layak bank. Kredit tidak mengalir ke desa, ironisnya justru terjadi pelarian modal dari desa ke kota. Subsidi pupuk dan bibit sering salah sasaran. Saat terkena puso, ganti rugi hanya janji. Ujung semua itu, produksi petani mahal dan dituding tidak mampu bersaing. Padahal, itu terjadi bukan sebab, tetapi akibat: akibat kebijakan yang meminggirkan.
Sebaliknya, peran negara dalam membantu korporasi swasta cukup besar. Salah satunya bisa dilihat dari perkebunan sawit. Lewat Program Perkebunan Besar Swasta Nasional pada awal 1980-an, perkebunan kelapa sawit mendapat subsidi suku bunga, kemudahan lahan, dan penyediaan tenaga kerja tak langsung lewat program transmigrasi. Selama 1991-2011, lahan perkebunan sawit besar naik dari 288.000 hektar jadi 5,23 juta hektar (naik 14 persen per tahun). Sebaliknya, total luas lahan perkebunan rakyat naik dari 10,7 juta hektar jadi 15,4 juta hektar (naik 1,7 persen per tahun). Ironisnya lagi, sebagian kebun sawit dimiliki asing. Data ini menunjukkan pengelolaan lahan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria 1960. Mengundang investor, termasuk asing, dan memberi lisensi ribuan hektar tak salah, tetapi menutup akses lahan petani itu salah besar dan mengusik nurani.
Apa makna dari fenomena ini? Dalam 400 tahun terakhir evolusi pembangunan selalu dibimbing oleh jiwa yang meniadakan petani/warga sebagai subyek pembangunan. Premis dasar kebijakan yang diyakini adalah usaha besar memiliki kapasitas lebih tinggi daripada petani. Padahal, bukti empiris menunjukkan sebaliknya.
”Sesat pikir” ini hanya bisa diakhiri apabila pertanian dan petani kembali dipandang sebagai pelaku utama: bukan saja tulang punggung ekonomi puluhan juta warga, melainkan juga penjaga stabilitas sosial-politik dan keutuhan NKRI. Lengsernya Soekarno dan Soeharto, diakui atau tidak, disulut perut warga yang lapar. Apa jadinya jika jutaan petani (kecil) emoh bertani?
Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010018975
-
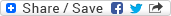
- Log in to post comments
- 539 reads