Saling bunuh, saling bakar sampai... ’sayang kamu semua’: Mantan tentara anak Islam dan Kristen Ambon
Endang Nurdin BBC Indonesia
27 Februari 2018
Ratusan anak diperkirakan terlibat dalam konflik paling berdarah Indonesia - Ambon- yang pecah pada 1999, terseret dalam arus kesadisan dan kebengisan perang.
Membunuh dengan berbagai senjata, parang sampai senjata api rakitan, membakar, mengebom, 'tanpa rasa (bersalah) apa-apa' sebagai 'mesin pembunuh', merupakan bagian hidup sehari-hari anak-anak berusia antara sembilan sampai belasan tahun saat itu, selama bertahun-tahun.
Kebencian membara atas nama agama - Islam, Kristen- membuat hidup mereka terkepung di lokasi konflik, dengan hanya satu tujuan "membunuh sebanyak-banyaknya lawan iman."
Pusaran konflik yang begitu dalam membawa mereka hanya pada dua pilihan: Dibunuh atau membunuh.
Dua di antara mereka, Ronald Regang dan Iskandar Slameth, menceritakan perjalanan mereka, berada di 'garis depan' saat konflik dan perjuangan berat menepis bara kebencian dan trauma mengingat orang-orang yang mereka bunuh dan kawan yang telah meninggal.
Keduanya pernah membunuh dengan alasan membela agama dan komunitas masing-masing.
Keduanya pernah disulut kebencian luar biasa satu sama lain, sampai kemudian bertemu di satu ruangan, beberapa tahun setelah konflik mereda, dan menjadi sahabat.
Ronald Regang: "Seandainya waktu bisa diputar"
"Seandainya saya bisa mengembalikan mereka punya nyawa… orang yang pernah saya bunuh… kawan-kawan yang meninggal, seandainya waktu bisa diputar kembali," kata Ronald satu malam di Ambon.
Ia tak berusaha menahan air matanya. Ia hanya mengusapnya.
"Kepala saya sakit," katanya beberapa kali menunjuk kepala bagian belakang saat bercerita tentang aksinya berada di garis depan dalam kerusuhan berdarah itu.
"Yang paling membuat saya trauma itu... orang-orang yang pernah saya bunuh, wajah-wajah mereka itu ada dalam tidur dan mimpi saya... Wajah mereka begitu kental dalam ingatan saya," katanya merunduk.
Pada awal tahun 2000, usianya baru menginjak 10 tahun. Namun ia telah dihadapkan dalam "kondisi membunuh atau dibunuh untuk bisa bertahan hidup."
Ronald tiba di pelabuhan di Teluk Ambon di akhir 1999, hampir satu tahun setelah konflik pecah pada 19 Januari 1999.
Saat itu konflik telah menyebar ke Ternate, tempat tinggalnya bersama orang tua serta kakak dan adik. Mereka sempat terpisah saat ibu dan adiknya mengungsi ke Manado terlebih dahulu dan kemudian ke Ambon. Ronald menyusul belakangan.
Kapal minyak yang tiba di pelabuhan khusus Kristen saat itu, langsung dirazia untuk "mencari orang Muslim."
"Yang paling saya ingat, tak ada orang di sepanjang jalan yang ada hanya kita, pasukan khusus, isi di dalam rumah-rumah dikeluarkan di jalan-jalan dibakar," cerita Ronald mengingat kejadian hampir 20 tahun lalu itu.
"Mayat-mayat ditumpuk… di kiri kanan, semuanya mayat. Sepanjang jalan bau amis, ada yang dibakar, ada yang membengkak, sepanjang jalan," tambahnya.
Seorang sepupu mengenalinya di pelabuhan dan langsung mengajaknya untuk bergabung bersama anak-anak lain yang malam itu "tengah mewarnai wajah mereka"
"Saya tak bisa kemana-mana lagi dan masuk ke medan pertempuran!"
Iskandar Slameth: "Mengungsi dibantu pela (saudara) Kristen"
Idul Fitri, 19 Januari 1999. Seorang pemuka masyarakat di salah satu permukiman Muslim Ambon, dipanah hingga tewas.
Kepanikan terjadi di tengah perayaan lebaran saat itu.
"Siapkan senjata apa adanya, kita harus mempertahankan diri," cerita Iskandar mengulang perintah ayahnya saat itu kepada anak-anak lakinya. Iskandar berusia 13 tahun.
Merasa tak aman di ibu kota Maluku itu, ayah Iskandar memutuskan untuk kembali ke kampung, Hitu, yang terhitung menjadi basis bagi komunitas Muslim.
Namun perjalanan dengan mobil selama sekitar satu jam ini penuh risiko karena harus melewati "kurang lebih 60% sampai 70% daerah orang Kristen," cerita Iskandar. Tak ada polisi atau militer yang mau mendampingi mereka.
Sejumlah gereja mundurkan jadwal ibadah demi 'dukung umat Muslim salat Idul Fitri'
Umat Buddha Indonesia penyumbang terbesar pembangunan RS di Rakhine. Buka puasa di gereja, kelompok pemuda lintas agama Cirebon jaga toleransi
Jalan-jalan dirintangi palang, menandai pemisahan wilayah Kristen dan Muslim.
"Saat melewati kawasan Kristen, pela mama di depan dan mereka bilang ini saudara saya… saat melewati wilayah Muslim, pela mama berada di belakang," tambahnya mengacu pada Pela Gandong, ikatan tali persaudaraan yang dibuat dengan satu upacara dengan mereka yang sebenarnya tidak memiliki pertalian darah.
"Berkat dia (pela Kristen) kita bisa sampai ke kampung."
"Saudara-saudara menyambut dengan Allahuakbar, karena mereka mengira kami sudah meninggal di Ambon," tambahnya.
Membunuh atau dibunuh
Namun beberapa bulan di kampung, Iskandar kembali ke Ambon - tersulut emosi- setelah mendengar kakaknya terkena bom dan "hancur kakinya".
Di sinilah, ia pertama kali membunuh, setelah ada orang yang menembaknya namun meleset.
"Saya membunuh atau dibunuh… ada abang teriak… lihat di belakangmu ada musuh. Parang masih di tangan… Saya emosi luar biasa karena ditembak. Sakit biar tak tembus tapi sakit. Dia mau potong saya, saya potong," cerita Iskandar.
Badannya penuh darah orang yang ditusuknya. Kejadian ini sempat membuatnya trauma.
"Saya mandi hingga bersih, salat sunah menenangkan diri… Kebayang terus, waktu dia berdarah…"
Perasaan saya seperti apa ya… tapi itu pilihan, saya membunuh atau saya dibunuh," katanya menahan emosi.
Perjalanan selanjutnya selalu dengan bom dan senjata.
"Darah saya mendidih... Saya dididik dengar bom dan senjata tiap hari. Saya juga sudah bunuh orang," tambahnya.
"Kita cukup sadis, (ada wilayah) yang kita bantai dalam satu hari."
Ia tergabung dalam Pasukan Jihad, sebutan untuk pasukan Muslim di Ambon. Saat konflik itu, katanya, terdapat dua kelompok lain, Laskar Jihad- yang datang dari luar Maluku- serta Mujahidin, kelompok dari luar Indonesia yang menempa ideologi mereka yang bertempur.
Saling menaruh dendam berat
"Selama perang terjadi, ada yang bersikap tenang, ada yang sangat emosional dan ingin membunuh.... Saya sendiri masuk dengan dendam, yang cukup kuat. Karena bukan kakak kandung saya saja yang kena bom. Saudara sepupu ditembak mati di tempat, sepupu dari ibu dipotong juga. Kalau bicara dendam, saudara saya banyak yang mati," kata Iskandar lagi.
Ronald memiliki sikap serupa. Tak lama setelah terlibat langsung di konflik, ia menjadi komandan Pasukan Agas, sebutan untuk tentara anak Kristen, memimpin lebih dari 20 anak-anak yang jadi milisi.
"Saat pertama kali membunuh, tak ada rasa apa-apa, karena saat itu dalam pikiran saya dan keluarga saya di kampung sudah dibantai dan saya ingin balas. Dan dalam diri saya, saat masuk perang dan membunuh orang tak ada rasa apa-apa," cerita Ronald.
Image caption Inilah salah satu lokasi pembunuhan, cerita Ronald.
"Sebelum masuk ke medan pertempuran, kita selalu melakukan doa. Karena anggapan kita saat itu adalah ini adalah perang suci, kita membela agama dan membela tempat tinggal kita," kata Ronald.
"Kita selalu awali dengan doa dan itu di gereja. Semua kumpul di gereja: kita membagi kawan-kawan, ada tim pembakar, tim pembom, tim penembak dan tim pemotong kita bagi-bagi untuk masuk (berbagai) daerah."
Sekitar 5.000 orang meninggal dan lebih setengah juta mengungsi dalam konflik sektarian dengan pusat di Ambon dan menyebar ke sebagian besar kepulauan Maluku.
Saat konflik mulai mereda, sejak perjanjian Malino yang dicapai pada 2002, para mantan tentara anak Ambon ini masih terkungkung bara dendam, dihantui orang-orang yang mereka bunuh, terbelut dalam trauma dan guncangan jiwa mendalam, menurut pendeta serta ustad pendamping mereka.
Ronald mengatakan ia baru berhenti memanggul senjata pada 2004, tahun saat ia didatangi Jacky Manuputty, pendeta yang diminta mencari anak-anak korban konflik di Indonesia oleh badan kanak-kanak PBB UNICEF untuk dipertemukan di Yogyakarta.
Bakar kebencian
Perjalanan ke luar Maluku ini mengawali perubahan Ronald.
"Ronald kecil saat itu melihat ada dunia lain, ada gedung-gedung tinggi," katanya tersenyum dengan mata berbinar. "Dari situ saya mulai berubah, saya bertemu dengan beberapa orang, termasuk psikolog dari Jakarta." Sebelumnya, kalau keluar dari Maluku, hanya sebatas Manado dan itupun saat mengungsi.
Ia mulai mengikuti berbagai kegiatan melalui Lembaga Antar Iman, yang dibentuk pendeta Jacky dan ustad Abidin Wakano.
Sementara Iskandar mengatakan ia terjebak dalam dunia gelap lainnya, narkoba.
"Perjalanan kita hanya di daerah Muslim, stres… tak bebas. Kita jalan situ lagi-situ lagi. Bisa ke sebelah, tapi ada rasa takut, saya dibunuh nggak?
"Onal hanya bilang kita paling sayang kamu semua"
Keengganan dan rasa takut untuk bertemu dengan warga Kristen membuat Iskandar terlambat untuk hadir ke salah satu acara perdamaian, Young Ambassador for Peace, pada 2006.
"Saat tahu mereka dari jihad mini, kami sudah hampir bunuh-bunuhan," kata Ronald mengacu pada kelompok Iskandar. "Kami kumpul dengan teman Muslim dan menyusun strategi kalau terjadi apa-apa," pungkas Iskandar dalam wawancara terpisah.
Selama lebih satu minggu mereka berada di penginapan dan baru pada hari ketiga kondisi mulai cair, pungkasnya.
"Kita tulis rasa benci, rasa dendam (di atas kertas)… Saya tulis saya paling benci sama Kristen, karena kakak saya hancur kakinya, sepupu saya mati. Lalu saya bakar semua (tulisan itu)," cerita Iskandar penuh emosi.
Ronald mengungkap kebencian yang sama. "Saya katakan kalau orang Muslim itu jahat, membunuh kita punya orang."
Image caption Ronald dan Iskandar: Kalau ada apa-apa dengan Is, saya yang maju demikian juga sebaliknya.
"Padahal kawan Muslim juga menceritakan hal yang sama. Kita bercerita isu orang Kristen kaya gini…. Lo kok isunya sama… kita sama-sama tak ada yang tahu."
Pertemuan ini menjadi titik balik berikutnya bagi kedua putra Maluku ini.
"Onal yang membuat kita semua benar-benar nangis…. Suasana hening, ada lilin… Onal tak banyak bicara… Onal hanya bisa bangkit dan bilang… Dia bilang kita paling sayang kamu semua," cerita Iskandar.
"Lebur sudah… teduh, nangis. Kita semua basudara (bersaudara)," tambah Iskandar. Lengannya merangkul mengingat pertemuan mereka sekitar 12 tahun lalu.
"Semua peluk erat, mulai hari ini sampai di mana pun kita saudara. Kamu mau pergi ke mana, bilang, beta akan di depan kamu," kenangnya.
"Saya merasa plong"
"Kita selama ini berperang, tapi kita tak tahu perang ini akan ke mana. Selama ini kita hanya melihat orang dengan mata sebelah. Kalau dengan mata dua atau ada dengan komunikasi, pasti tak ada kerusuhan atau kita tak saling bunuh," kata Ronald lagi.
Sejak pertemuan itu mereka saling mengundang untuk bertandang ke daerah masing-masing.
"Pas saya menginjak kaki di daerah Kristen, saya merasa plong. Ini namanya bebas. Balik ke rumah dalam keadaan baik-baik," kata Iskandar.
"Kita berkomitmen untuk jadi duta damai diri sendiri dan orang-orang di samping kita. Kita diajarkan sebagai mediator."
"Kita keluar dari situ dengan penuh kesenangan. Satu kampung Kristen misalnya… yang dulu habis dalam satu hari... Mereka punya dendam terhadap saya… Namun saya ke sana pergi makan ikan bakar ramai-ramai."
"Sesudah itu, kita melangkah: ada saudara di sini, di sana. Tak punya rasa takut lagi…Tak ada lagi, lepas…," kata Iskandar.
Artikel ini merupakan bagian pertama dari beberapa tulisan tentang kisah mantan tentara anak Ambon.
Produksi visual oleh Haryo Wirawan.
(Kisah Ronald Regang yang ditulis Jacky Manuputty termasuk salah satu cerita dalam buku 'Keluar Dari Ekstremisme, Delapan Kisah Hijrah dari Kekerasan Menuju Binadamai yang diluncurkan pada 27 Februari 2018. Saat ini Jacky adalah asisten Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antariman dan Antarperadaban.)
-
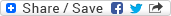
- Log in to post comments
- 110 reads