Oleh Mohammad Abduhzen
Rancangan Kurikulum 2013 mengembalikan Pancasila seperti Kurikulum 1994, yaitu sebagai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Keberadaan Pancasila dalam kurikulum senantiasa timbul tenggelam, bergantung pada situasi kebangsaan. Pada Kurikulum 1968, di awal Orde Baru, Pancasila menjadi kategori pertama bidang pembelajaran ”Pembinaan Jiwa Pancasila” yang terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olahraga.
Kurikulum 1975—seiring menguatnya dominasi Orde Baru—menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kurikulum ini disempurnakan pada 1984 dengan menambahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), di samping PMP dan Sejarah. Tumpang tindih pelajaran ini kemudian disederhanakan dalam Kurikulum 1994 dengan menyatukan PMP dan PSPB jadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Ketika Reformasi tiba, Pancasila yang lama menjadi alat legitimasi turut mengalami deapresiasi sehingga UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tak mewajibkan Pancasila ada dalam kurikulum pendidikan. Karena itu, dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 2006), Pancasila raib dan PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Kevakuman
Proses ideologisasi Pancasila semasa Orde Baru dengan tafsir dan asas tunggalnya telah memaksa mayoritas masyarakat Indonesia berideologikan Pancasila secara semu. Praktik represif dan doktrinal yang ditempuh justru menimbulkan sinisme terhadap Pancasila sebagai personifikasi penguasa. Maka, saat Orba jatuh, Pancasila seperti ikut melindap.
Sekarang, Pancasila mengalami kekosongan makna karena pemaknaan oleh Orde Baru berupa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) beserta 36 butir nilai-nilai seolah gosong. Kita perlu rekonstruksi tafsir yang mampu menerangkan bagaimana berbagai gagasan dalam Pancasila saling berhubungan dan mampu mengantarkan bangsa ini pada kehidupan lebih baik, seperti janji kemerdekaan.
Pada hari-hari ini, kita juga tak menyaksikan adanya upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan secara mendasar dan sistemis. Memang ada upaya sosialisasi ”Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, tetapi—selain Pancasila sebagai pilar dipersoalkan—hanya sayup-sayup sampai kepada publik. Barangkali kita tinggal mengandalkan kecakapan para guru mengajarkan Pancasila di sekolah. Itu pun, sekarang ini, Pancasila diajarkan sebatas dasar administrasi negara.
Menguatnya semangat aliran belakangan ini di ranah politik dan sosial merupakan indikator kian lemahnya apresiasi masyarakat terhadap Pancasila sebagai landasan hidup bersama. Kenyataan ini tak boleh dibiarkan, dan seyogianya pemerintah serius merevitalisasi Pancasila.
”Mengilmiahkan” Pancasila
Butir penting untuk reaktualisasi yakni merumuskan konstelasi pembelajaran dan transformasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan.
Sebagai substansi pembelajaran, Pancasila selama ini dikenalkan lebih sebagai mitos ketimbang sesuatu yang ilmiah. Keberadaan Pancasila seperti tak melekat dalam kesadaran dan hanya muncul sebagai perilaku artifisial. Agar mengejawantah sebagai perilaku otentik, Pancasila harus diakarkan di dalam pikiran dan ditumbuhkan sebagai sikap di dalam jiwa.
Karena itu, Pancasila perlu ”diilmiahkan” dengan mengobyektivikasi makna-makna normatif dan simbolisnya secara logis-empiris. Pembahasan Pancasila harus mampu mengantarkan kita kepada situasi logika dan fakta yang tak terelakkan sehingga pilihannya harus diterima.
Pancasila, sebagaimana dinyatakan penggagasnya, adalah philosofische grondslag atau weltanschauung, yaitu fundamen, filsafat, dan pikiran yang mendalam. Pancasila lahir sebagai antitesis imperialisme dengan ide-ide besar seperti ”penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”, kebinekaan/pluralisme, musyawarah, dan ketuhanan yang harus dijadikan realiteit.
Merealisasikan Pancasila sebagai landasan kehidupan bersama, yang dibutuhkan di alam modern ini, memerlukan argumen yang tak sekadar common sense, akal sehat. Setakat ini status epistemologis Pancasila baru sebatas deskripsi tentang realitas dan cita-cita. Ini tergambar dari pidato Soekarno tentang sila Ketuhanan: ”bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan.”
Pembahasan Pancasila tidak cukup dan berhenti sebatas konsep-konsep universal, tetapi harus berlanjut ke tataran operasional dan kontekstual berdasarkan situasi, kebutuhan, dan pengalaman kebangsaan kita sendiri. Ibarat pohon, Pancasila tunduk pada hukum pertumbuhan universal, tetapi sejatinya ia tetumbuhan tropis.
Reinterpretasi untuk reaktualisasi Pancasila telah dimulai Yudi Latif dengan karyanya Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2010). Yudi mengobyektivikasi Pancasila dengan fakta historis dan pendekatan teoritis-komparatif, disusul gagasan rasional bagaimana sila demi sila seharusnya diaktualkan.
Pendidikan, tafsir, dan pemikiran tentang Pancasila perlu dikemas sedemikian rupa agar menjadi nilai-nilai kepribadian (kompetensi) lulusan.
Problem metodologi
Selain persoalan substansi, pembelajaran Pancasila di sekolah sering kali terkendala faktor metodologi. Pada satu sisi disampaikan terlampau akademis—diajarkan hanya sebagai fakta pengetahuan—dan pada sisi lain terlewat ideologis (memaksakan nilai-nilai sebagai doktrin).
Pembelajaran harus menjadi upaya penyadaran pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Metode ini seharusnya dapat diturunkan dari UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) yang menekankan pentingnya penciptaan suasana dan proses pembelajaran, keaktifan, dan berpusat pada murid. Sayangnya, rancangan Kurikulum 2013 tak mengelaborasi metode pembelajaran secara utuh dan menyeluruh. Elemen perubahan terkait proses pembelajaran hanya menambahkan kata teknis: ”mengamati, menanya, dan mengolah”. Sementara pendekatan tematik-integratif dikhususkan untuk SD karena sebelumnya pelajaran IPA akan diintegrasikan di semua kelas SD.
Pendidikan Pancasila mendatang potensial mengalami disorientasi karena ada reduksi dan kesenjangan logika pada kompetensi kurikulum. Kompetensi inti sebagai sublimasi perolehan dari seluruh mata pelajaran mengerutkan fungsi pendidikan hanya dalam empat kategori yang rancu, yakni sikap keagamaan, sikap sosial, pegetahuan, dan penerapan pengetahuan.
Sebagai tujuan akhir pembelajaran, kompetensi inti, selain tampak begitu miskin, juga menimbulkan masalah tautan logis dengan kompetensi dasar dan sesi-sesi pembelajaran, terlebih untuk Pendidikan Pancasila. Menyaksikan situasi kebangsaan yang kian mengkhawatirkan akhir-akhir ini, perumusan Pendidikan Pancasila harus berspektrum luas dan menjadi bagian dari strategi nation building.
Mohammad Abduhzen Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta; Ketua Litbang PB PGRI
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2013/04/26/02240329/pendidikan.pancasila
-
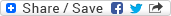
- Log in to post comments
- 420 reads