Kamis, Jan 23 2014
Ditulis oleh amex
Jika mencermati pada perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sepuluh tahun terakhir, justeru memperlihatkan suatu kondisi yang lebih dominan terjadinya gesekan-gesekan konfliktual ketimbang nuansa harmonis masyarakat. Anggapan banyak pihak mengenai adanya krisis pemerintahan dan tuntutan reformasi (tanpa platform yang jelas) telah menimbulkan berbagai ketidakmenentuan dan kekacauan. Acuan kehidupan bernegara (governance) dan kerukunan sosial (social harmony) menjadi berantakan dan menumbuhkan ketidakpatuhan sosial (social disobedience). Dari sinilah berawal tindakan-tindakan anarkis, pelanggaran-pelanggaran moral dan etika, pelanggaran hukum dan meningkatnya kriminalitas. Ketika kondisi ini terus terjadi secara berkepanjangan dan tidak jelas kapan krisis ini akan berakhir, para pengamat hanya bisa mengatakan bahwa bangsa kita adalah “bangsa yang sedang sakit”.
Sifat pluralistik bangsa kita belum memberi ruang yang ideal bagi berkembangnya budayabangsa dan agama yang dianut oleh warganegara. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sukubangsa dan kebudayaan agama, belum secara bersama-sama menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewarnai perilaku dan kegiatan kita. Berbagai kebudayaan itu tampak berjalan sendiri-sendiri, belum saling melengkapi dan saling mengisi, sehingga belum mampu untuk saling menyesuaikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kebangsaan Multikultural
Sepuluh tahun terakhir, dan ketika bangsa kita terwarnai oleh semakin tajamnya relasi sosial yang tidak mengenakkan, pada saat yang sama mencuatlah diskursus “baru” – dalam arti kembali dibangkitkan – untuk memberikan respon terhadap situasi sosial yang memprihatinkan. Diskursus tersebut adalah multikulturalisme yang secara konseptual merujuk pada beberapa pemikir kebudayaan seperti Bhikhu Parekh, Gayatri Chakravorty Spivak, Homi K Bhabha, dan sebagainya. Di dalam bukunya,Rethinking Multiculturalism, Bhikhu Parekh mengatakan bahwa gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia sekitar tahun 1970-an, kemudian menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya.
Bagi para pemikir kebudayaan, multikulturalisme tidak sekedar sebuah konsep mengenai pentingnya pengelolaan keberagaman masyarakat, melainkan juga perlu dikembangkan menjadi sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Dengan diarahkan sebagai sebuah ideologi, maka ia akan secara mudah bergandengan tangan dan saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi dan perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia.
Masyarakat Indonesia sendiri diakui sebagai masyarakat yang majemuk, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan masyarakat berideologi multikulturalisme. Sejauh ini, kemajemukan masyarakat Indonesia masih banyak diwujudkan dalam warna-warni perbedaan budaya, suku, ras, agama, dan jender tetapi warna-warni tersebut belum menjadi dasar dan urat nadi bagi sebuah desain pembangunan bangsa. Ironisnya, dalam kehidupan masyarakat majemuk, perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik yang dikukuhkan sebagai hukum ataupun sebagai konvensi sosial justru kerap berujung pada pembedaan antara mereka yang tergolong sebagai dominan dengan kelompok minoritas. Sejak zaman Hindia Belanda, terdapat golongan yang paling dominan yang berada pada lapisan teratas, yaitu orang Belanda dan orang kulit putih, disusul oleh orang Cina, Arab, dan Timur asing lainnya, dan kemudian yang terbawah adalah mereka yang tergolong pribumi. Sementara untuk masyrakat pribumi pun masih digolongkan lagi menjadi kelompok masyarakat yang tergolong tidak mengenal peradaban (uncivilized) dan meraka yang telah mengenal peradaban (civilized).
Relasi sosial antara kelompok dominan dengan kelompok minoritas memunculkan suatu prestise dan perlakuan sosial yang berbeda pula. Kelompok dominan hampir selalu dan kerap menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak dan pada akhirnya membentuk struktur mental untuk meneguhkan diri sebagai kelompok yang merasa berhak menguasai seluruh dimensi kehidupan dimana mereka tinggal. Bahkan, untuk meneguhkan superioritas dan dominasinya itu, kelompok mayoritas kerap mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang ada dalam masyarakatnya. Pada akhirnya, kelompok dominan ini merasa berhak menguasai akses sumber daya yang ada dan selalu merasa takut jika suatu saat kelompok minoritas akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut.
Konsep dan ideologi multikulturalisme dibangun dan dikembangkan untuk merespon pembedaan-pembedaan dalam bentuk ketidaksetaraan relasi antara kelompok dominan dengan kelompok minoritas yang arahnya adalah membentuk masyarakat anti-diskriminasi. Oleh sebab itu, sebagian dari kalangan yang mengedepankan adanya multikulturalisme-ideologis, perjuangan anti-diskriminasi dan perjuangan hak-hak hidup dalam kesederajatan dari minoritas harus disetarakan sebagai suatu perjuangan politik yang berarti adalah perjuangan kekuatan. Antropolog Parsudi Suparlan pernah mengemukakan bahwa perjuangan yang akan memberikan kekuatan kepada kelompok-kelompok minoritas sehingga hak-hak hidup mereka dapat dipertahankan dan tidak didiskriminasi oleh kelompok –kelompok yang menganggap sebagai kelompok dominan. Perjuangan politik seperti ini menuntut adanya landasan logika yang masuk akal di samping kekuatan nyata yang harus digunakan dalampenerapannya. Logika yang masuk akal tersebut ada dalam multikulturalisme dan dalam demokrasi.
Kearifan Lokal sebagai Basis
Sebagai bangsa dengan masyarakat yang majemuk, setiap kelompok masyarakat pastilah memiliki sudut pandang, cara, keyakinan, nilai dan pedoman hidup dalam mengarungi kehidupannya. Seperangkat nilai-budaya itu yang kemudian didefinisi oleh para ilmuan sebagai kearifan lokal, terjemahan dari istilah local wisdom. Logika yang terdapat dalam kearifan lokal adalah keniscayaan adanya masing-masing kelompok yang memiliki “keunikan” wajah budayanya dan mungkin terdapat nilai-nilai tertentu yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai budaya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang lain.
Di sinilah perlunya untuk secara berhati-hati menempatkan dan menggamit istilah kearifan lokal dalam konteks masyarakat heterogen masa kini yang penuh dengan gesekan-gesekan. Relativitas kebudayaan yang terusung dalam istilah kearifan lokal dapat menjadi blunder sosial jika tidak dikelola dengan baik karena masing-masing masyarakat akan dapat mengklaim bahwa nilai budayanya yang paling baik dah harus dirujuk sebagai dasar pembangunan bangsa. Politik primordialitas dan etnokarsi (kekuasaan berdasarkan etnisitas) tidak jarang yang disebabkan oleh keadaan ini jika tidak mampu dijaga dengan baik.
Oleh sebab itu, kearifan lokal yang beraras pada “keunikan” nilai budaya dari ragam masyarakat Indonesia harus dirembuk bersama hingga kemudian diambil sisi-sisi pendorong bagi arah pembangunan bangsa yang berkarakter. Dialog antar kekuatan budaya harus terus-menerus digelar dalam rangka menemukan sari-budaya yang menggugah semangat kebangsaan yang penuh dengan kearifan. Jika hal ini dapat dilakukan, maka kita tidak perlu terlalu risau dengan percepatan perubahan sosial yang dapat berimplikasi pada ketidakjelasan karakter kebangsaan kita. (*)
-
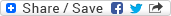
- Log in to post comments
- 436 reads