National Geographic Indonesia - Kamis, 29 Agustus 2019 | 15:27 WIB
Nationalgeographic.co.id - Umpatan nama binatang yang digunakan oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) dan aparat untuk mengintimidasi mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, selain melahirkan gelombang solidaritas #kamibukanmonyet, juga menyulut rusuh di berbagai kota di Indonesia.
Peristiwa di Surabaya bukan kali pertama menimpa orang Papua. Sebelumnya sempat juga terjadi di Malang, Jawa Timur; Semarang, Jawa Tengah; dan Yogyakarta. Selain politis, sebagian musababnya soal sepele atau salah paham.
Sikap terhadap kelompok orang yang berbeda ini cenderung mengarah pada penolakan atau bahkan kekerasan. Padahal menurut riset saya, orang Papua cenderung terbuka terhadap perbedaan.
Masyarakat Indonesia banyak yang memiliki persepsi orang Papua sebagai orang yang sulit bergaul atau beradaptasi , dan persepsi ini yang menguat belakangan.
Pola hidup sebagian orang Papua yang masih sederhana dikaitkan anggapan bahwa orang Papua sulit menghadapi perbedaan. Namun benarkah, demikian?
Koroway yang lestari sekaligus terisolasi
Pada 2017, saya bersama melakukan riset pada komunitas Koroway (Korowai) di Kampung Yafulfa, Boven Digul, di selatan Papua dengan metode etnografi mengenai kelestarian arsitektur tradisional rumah pohon (luop haim) serta memahami praktik tradisi di tengah dinamika sosial-ekonomi yang terjadi di papua.
Dalam penelitian yang saya lakukan, saya juga melihat bagaimana komunitas pedalaman Koroway masih bisa menghargai perbedaan meski hidup dalam lingkungan yang terisolir. Riset saya menunjukkan bahwa pada komunitas yang masih hidup bersahaja ini, mereka cukup bisa menerima perbedaan.
Suku Koroway baru melakukan kontak dengan dunia luar pada tahun 1978 saat bertemu misionaris Belanda dan sebelumnya hidup tersebar di bolup (area bermukim dan tempat berburu sesuai marga).
Bolup tetap ada sebagai area berburu dan meramu, serta menjadi lokasi untuk menyaksikan pesta ulat sagu atau rumah tinggi.
Meskipun orang Koroway sudah merasakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil dari Kementerian Sosial, hidup mereka masih terisolasi. Akses jalan darat dan fasilitas pendidikan serta kesehatan terbatas.
Keterisolasian itu menciptakan situasi keterasingan yang unik, sehingga proses interaksi orang Koroway dengan yang liyan tidaklah intensif.
Lantas, apakah situasi orang Koroway yang sangat sedikit bersentuhan dengan dunia luar membuat mereka bereaksi keras terhadap sesuatu yang berbeda? Riset saya menyatakan sama sekali tidak tidak.
Saya bersama peneliti lainnya masuk ke dalam hutan untuk melihat keseharian hidup orang Koroway ketika berada di dalam bolup. Pada satu kesempatan di bolup, salah satu anggota tim peneliti meminta ijin untuk menunaikan sholat.
Islam sudah akrab terdengar oleh banyak orang Koroway, tapi mereka tidak pernah menyaksikan seperti apa dan bagaimana Islam itu. Islam adalah sesuatu yang benar-benar asing dan jelas berbeda bagi orang Koroway.
Lantas, bagaimana reaksinya? Apakah rekan peneliti saya kemudian dilarang untuk menggelar sajadahnya?
Rupanya tidak. Pemuka marga mempersilakan anggota tim untuk menjalankan ibadahnya. Orang Koroway memperlakukan dia dengan penuh hormat.
Usai ritual sholat, barulah orang Koroway bertanya mengenai ritual yang baru kali pertama mereka saksikan. Mereka berkesimpulan, “Oh, sama seperti kami; kami juga beribadah. Hanya beda saja caranya.”
Bahkan, orang Koroway dapat secara spontan mencari titik temu persamaan dari perbedaan itu: jika kami beribadah, maka orang lain pun sama, hanya saja caranya berbeda. Bukan suatu permasalahan.
Interaksi spontan itu menunjukkan tidak adanya pertentangan antara pola hidup tradisional dengan pola interaksi dalam konteks keberagaman.
Kekerasan karena perbedaan
Di Indonesia, persepsi perbedaan yang berujung rasisme jarang dipermasalahkan.
Misalnya, pandangan merendahkan soal orang Papua suka mabuk, bahkan soal aroma tubuh mereka tidak jarang terucap. Sebagian kita tetap melihat rasisme terhadap mahasiswa Papua ini suatu tindakan yang normal.
Ini tidak lain karena seringkali sentimen kebencian hadir dalam persoalan yang begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita, sehingga kita tidak mengkritisinya dan menganggapnya sebagai pola interaksi yang wajar.
Padahal seringkali perbedaan persepsi ini bisa menimbulkan kekerasan.
Hal ini karena pemerintah gagap dalam merespons rasisme terhadap Papua.
Akibatnya, persepsi negatif terhadap warga Papua, menurut mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, menguat dalam beberapa tahun terakhir ini.
Politisasi perbedaan
Pada hakikatnya sifat manusia atau suatu norma budaya tidaklah menentukan etika, sebagaimana yang disampaikan oleh antropolog asal Amerika Serikat Webb Keane.
Secara alami, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada dorongan untuk memperlakukan orang lain secara setara dan etis, sebab kita pun menyadari ingin diperlakukan seperti itu.
Lantas, mengapa rasisme yang berujung kekerasan ini bisa muncul?
Segala gagasan rasisme dan segala bentuk sentimen kebencian seringkali adalah hasil dari politisasi atas perbedaan itu sendiri.
Riset Ivana Macek, antropolog Kroasia, dalam buku etnografi Sarajevo Under Siege melihat menguatnya persoalan etno-nasionalis di Bosnia – yang sebelumnya hidup bersama dengan damai – ketika Yugoslavia runtuh, adalah tidak lain akibat politisasi perbedaan.
Politikus di sana menjadikan perbedaan etnis-agama sebagai komoditas politik dan memaksa publik untuk membenci orang lain yang identitasnya berbeda.
Bagaimana di Indonesia? Perlu sekiranya kita – publik Indonesia, merenungkan, apakah kita benar-benar meyakini kebhinnekaan.
Apakah kebhinnekaan sudah tercermin dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, ataukah kita dirasuki oleh suatu kepentingan politis?
Bangsa ini banyak merekam banyak kasus perbedaan yang dipolitisasi, mulai dari soal stigma atas komunis, pelaku kriminal , hingga penganut keyakinan minoritas dan orientasi seksual.
Dalam kasus-kasus itu pemerintah berperan menjadi aktor utama atas terjadinya politisasi perbedaan lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
Masalahnya, keterlibatan pemerintah tidak saja berpengaruh pada masalah, tapi dapat mengubah persepsi publik. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah menghentikan produksi ketakutan atas perbedaan dalam segala rupa atributnya.
Tidakkah kita sebaiknya meneladani orang Koroway yang secara alami dan dalam kesehariannya tidak melihat perbedaan sebagai masalah?
Penulis: Irfan Nugraha, Associate researcher, Universitas Indonesia
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber https://theconversation.com/peneliti-kita-perlu-belajar-dari-suku-koroway-di-papua-tentang-perbedaan-122349
-
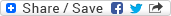
- Log in to post comments