Di Pulau Morotai, pulau kecil di ujung utara beranda negeri ini, seorang petugas penginapan berkelakar bahwa ada 2 (dua) buah matahari yang Tuhan ciptakan di pulau berpenduduk 74.565 jiwa (2020) ini. Kelakar ini bertolak dari suhu udara di permukaan bumi yang terasa jauh lebih panas ketimbang lima tahun sebelumnya.
Tak hanya warga Pulau Morotai, keluhan mengenai Bumi yang memanas ini juga dilontarkan oleh penduduk Indonesia lainnya. Menariknya, semua orang ikut merasakan meski memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tak terkecuali para pemangku kebijakan (policymakers). Pertanyaannya, apa yang sesungguhnya tengah terjadi di muka Bumi ini?
Para ahli sains terkemuka yang tergabung di dalam Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menerbitkan laporan terbaru berjudul Climate Change 2023: Synthesis Report pada bulan Maret 2023. Di dalam ringkasan laporan yang ditujukan kepada policymakers, para ilmuwan menyampaikan bahwa suhu rata-rata di Bumi telah meningkat 1,1 derajat celsius sejak 1880 dengan laju pemanasan di Indonesia lebih cepat. Suhu Bumi diperkirakan bakal melewati titik kritis 1,5 derajat celsius dalam lima tahun mendatang. Jika hal ini dibiarkan, niscaya generasi mendatang bakal menanggung beban besar dari pemanasan global.
Di dalam publikasi terbaru berjudul Quantifying the human cost of global warming (2023) yang dimuat di jurnal Nature Sustainability, Timothy M. Lenton menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat ketiga setelah India dan Nigeria yang merasakan dampak terbesar dari kenaikan suhu global, disusul oleh Filipina, Pakistan, dan Sudan. Lantas, apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari memanasnya suhu bumi ini?
Berkaca pada Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045 yang dilansir oleh Kementerian PPN/Bappenas, disebutkan bahwa sejumlah ancaman perubahan iklim yang terjadi di negeri kelautan ini adalah tinggi gelombang ekstrem meningkat > 1,5 meter, tinggi permukaan laut meningkat 0,8-12 cm per tahun, peningkatan suhu 0,45-0,75 derajat celsius, dan curah hujan lebih dari 2,5 mm per hari. Sejumlah ancaman perubahan iklim ini nyata terjadi di depan mata. Terlebih lagi di sektor perikanan.
Dalam perspektif nelayan, sebagaimana didokumentasikan oleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (2023), terdapat 3 (tiga) dampak perubahan iklim yang mereka alami, yakni perubahan musim melaut, pembengkakan biaya melaut, dan perubahan hasil tangkapan ikan. Ketiga hal ini kian memburuk seiring perubahan kebijakan perikanan nasional yang eksploitatif.
Seperti ditengarai oleh FAO (2018), tingkat eksploitasi sumber daya ikan yang tidak terkontrol dan memuncak antara tahun 1970-1980 menjadi penyebab utama menurunnya tren produksi perikanan tangkap di dunia. Hal ini berimbas pada merosot tajamnya tingkat keberlanjutan biologis (biologically sustainable levels) stok sumber daya ikan, dari 90 persen (1974) menjadi 66,9 persen (2015).
Setali tiga uang, tingkat ketidakberlanjutan biologis (biologically unsustainable levels) stok sumber daya ikan justru meningkat, yakni 10 persen pada tahun 1974 menjadi 33,1 persen pada tahun 2015. Tak mengherankan apabila sejumlah spesies ikan dilaporkan kian sulit ditemukan oleh nelayan dalam 20 tahun terakhir.
Di Kabupaten Lombok Timur, misalnya, nelayan menyebut adanya sejumlah spesies ikan yang terbilang langka sejak tahun 2010, di antaranya adalah ikan selangat (Anadonstoma chacunda). Hal serupa besar kemungkinan bisa terjadi pada rajungan (Portunus pelagicus) yang memiliki estimasi potensi sebesar 57.947-ton (2022) apabila prinsip-prinsip pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab diabaikan. Kenapa demikian?
Tak dimungkiri, perikanan merupakan sumber pangan dan nutrisi, mata pencaharian, dan penyumbang pertumbuhan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat dunia. Saking signifikannya, desakan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab disuarakan oleh pelbagai pihak.
Salah satu ciri khas perikanan dan sekaligus menjadi tantangannya adalah ketidakpastian perikanan (fisheries uncertainty) yang bersumber pada ketidakpastian alamiah (natural uncertainties) dan ketidakpastian manusia atau human uncertainties.
Tujuan tata kelola perikanan adalah untuk menjamin keberlanjutan perikanan itu sendiri. Namun, mesti disadari bahwa keberlanjutan perikanan tidak terbatas di dalam konteks eko-biologi semata, melainkan juga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ditopang oleh tata kelola perikanan yang baik.
Adanya skandal perikanan di Eropa Utara pasca terbitnya laporan bertajuk Konsentrasi Kuota Perikanan di Denmark yang dipublikasikan oleh Rigsrevisionen (Kantor Audit Nasional Denmark) pada Agustus 2017 menunjukkan bahwa polemik manajemen sumber daya perikanan (fisheries management) memiliki keterkaitan dengan perilaku manusia (human behaviour).
Skandal yang terjadi di Denmark ini bermula dari adanya temuan monopoli penguasaan 66 persen kuota penangkapan ikan oleh 16 pebisnis pada tahun 2017, yang terjadi karena Kementerian Pangan dan Lingkungan Hidup Denmark absen dalam menyusun perangkat regulasi dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel guna mengontrol kuota perikanan tersebut.
Pada perkembangannya, seperti dilaporkan oleh Rigsrevisionen, ditemui sejumlah fakta yang mencederai prinsip keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, yakni pertama, kuota perikanan hanya dimiliki oleh 16 pebisnis dengan tingkat penguasaan mencapai 2/3 atau 66 persen dari total keseluruhan kuota tangkapan ikan pada tahun 2017. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2012, yakni sebesar 53 persen. Dari jumlah tersebut, 10 pemilik kuota perikanan di antaranya memiliki rata-rata penguasaan sumber daya ikan hingga 47 persen dihitung berdasarkan kapasitas kapal ikan yang dimiliki.
Kedua, laporan Rigsrevisionen juga menyebutkan bahwa Kementerian Pangan dan Lingkungan Hidup Denmark absen dalam menyusun perangkat regulasi dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel guna mengontrol pelaksanaan kebijakan kuota perikanan berbasis individu tersebut. Imbasnya, praktek monopoli di dalam pengelolaan sumber daya perikanan kian menggurita. Tak hanya di Denmark, praktek serupa juga terjadi di Perancis. Inilah pelajaran berharga yang semestinya dijadikan sebagai acuan oleh policymakers di sektor perikanan dalam negeri.
Alih-alih belajar dari Denmark dan Perancis, polemik manajemen sumber daya perikanan justru kembali marak pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Betapa tidak, ada 3 (tiga) poin yang melemahkan posisi Indonesia sebagai produsen perikanan kedua terbesar di dunia, yakni pertama, di dalam regulasi ini, usaha penangkapan ikan kembali dibuka untuk penanaman modal asing; kedua, diperbolehkannya alih muatan ikan dari pelabuhan pangkalan di dalam negeri ke pelabuhan negara tujuan dilakukan dengan menggunakan kapal kargo ikan berpendingin berbendera Indonesia atau berbendera asing; dan ketiga, pelemahan upaya penegakan hukum di sektor perikanan melalui penerapan sanksi administratif.
Dengan pemberlakuan ketiga poin di atas, sepertinya kealpaan untuk belajar dari sejarah masih menjangkiti policymakers di sektor perikanan. Sejarah mencatat, anjloknya stok ikan di 11 WPP-NRI disebabkan oleh perilaku policymakers sendiri, di antaranya adalah pembolehan pemakaian alat penangkapan ikan yang merusak; penerbitan administrasi perikanan dengan mengabaikan fakta dan data di lapangan; maraknya penangkapan ikan ilegal. Ketiga faktor inilah kemudian yang mendorong terjadinya praktek penangkapan ikan yang berlebih dan memicu lahirnya praktek perbudakan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh awak kapal dan tenaga kerja di sektor perikanan.
Belum lekang dari ingatan publik, pada tahun 2015, penyelamatan besar-besaran terhadap nelayan asing yang dieksploitasi sebagai tenaga kerja bagi kapal penangkap ikan yang terlibat di dalam praktek IUU Fishing mencerminkan adanya kebijakan yang tidak memadai dari industri perikanan dan minusnya perlindungan hak-hak ketenagakerjaan di sektor perikanan nasional.
Jalan keluar
Bung Hatta pernah berpesan bahwa, “Indonesia merdeka bukanlah tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat”. Bertolak dari pesan ini, terdapat sejumlah langkah strategis yang mesti dilakukan oleh policymakers di sektor perikanan, yakni pertama, mengedepankan pengelolaan perikanan berbasis WPP-NRI sesuai dengan kekhasan sumber daya ikan yang dimiliki dan diorientasikan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan kemakmuran pelaku usaha nasional, mulai dari nelayan kecil, pemilik kapal hingga pengolah/pemasar ikan skala besar.
Kedua, ikan merupakan sumber nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kecerdasan umat manusia. Tak pelak, sejumlah negara, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea, habis-habisan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan global.
Ketiga, sumber daya ikan merupakan kekuatan budaya yang berurat akar di dalam sejarah peradaban manusia Indonesia. Di sinilah pentingnya pemerintah berperan untuk memastikan bahwa sumber daya ikan yang dimiliki bangsa Indonesia bisa diolah, dikonsumsi, dan diwariskan sebagai kekayaan budaya nasional yang mesti dilestarikan dari masa ke masa.
Akhirnya, laut adalah ruang pemersatu, sumber kesehatan dan kecerdasan bagi anak-anak negeri, dan menjadi kekuatan kultural yang menautkan pelbagai suku bangsa di tanah air. Dengan ketiga jalan keluar inilah, niscaya kemakmuran bisa dihadirkan di laut. Mari katong jaga bae-bae!
Sumber: https://biodiversitywarriors.kehati.or.id/opini/menghadirkan-kemakmuran-di-laut/
-
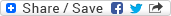
- Log in to post comments