Oleh : R. Jemmy Talakua
Tulisan ini sebenarnya terinspirasi pengamatan dan refleksi terhadap ”pasar” sebagai media aktivitas ekonomi yang sesungguhnya juga memiliki wajah baru sebagai wahana rekonsiliasi saat konflik terjadi di Ambon. Pasar sebagai sarana publik tersebut merupakan tempat vital yang biasanya mempertemukan masyarakat Ambon dari beragam latar belakang baik agama, suku, budaya, strata sosial dll untuk berbagai kepentingan dan diantaranya kepentingan mencari hidup untuk menghidupi keluarga.
Dalam penulisan ini penulis lebih berkonsentrasi pada ’pasar kaget[1] dan papalele[2]’ sebagai sebuah media ekonomi tradisional dan juga media publik yang memiliki kontribusi dalam menciptakan rekonsiliasi di Ambon. Pernyataan ini bermaksud untuk memperlihatkan dimensi lain dari pasar tetapi di sisi lain penulis mengakui bahwa pasar juga merupakan tempat yang rentan dengan konflik. Hal yang hendak dianalisa adalah dimensi pasar apa sajakah yang telah menjadi katalisator rekonsiliasi tersebut.
Eksistensi Pasar di Kota Ambon.
Pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, politis dan lain-lainnya. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pasar tidak bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata (tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar-menukar uang dan barang) tetapi juga memiliki dimensi lain yang saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, praktek ekonomi dalam bentuk pasar tersebut tidak setua peradaban manusia karena banyak masyarakat tradisional yang dapat hidup tanpa adanya pasar sejak awalnya.
Memang lahir dan berubahnya orientasi pasar sejak semula tidak hanya dipengaruhi oleh tuntutan kebutuhan hidup manusia (ekonomi subsistensi : mencukupi kebutuhan hidup) tetapi juga kebutuhan lainnya yang terus berkembang (politik, kekuasaan dll). Peran pasar yang tidak selamanya berfungsi untuk memperkuat tatanan ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi sosial, politik, budaya dan lain-lain. Meskipun fungsi-fungsi tersebut bisa saling memanfaatkan satu sama lain dan bahkan demi tujuan yang tidak proporsional.
Disaat konflik komunikasi antar warga terputus dan akses ke pasar semakin terbatas. Masing-masing komunitas sosial (Islam dan Kristen) tetap berada pada wilayahnya sendiri, sementara konflik terus bereskalasi tinggi. Dalam kondisi seperti ini terdapat kelompok-kelompok masyarakat pada kedua komunitas yang secara sembunyi-sembunyi dan penuh resiko saling berkomunikasi dan mengadakan transaksi kebutuhan pangan untuk dijual kepada masyarakat di lingkungannya. Kelompok dengan kepentingan ekonomi[3] ini berinisiatif untuk membuka kebekuan akibat pertikaian dan hidup yang tersegregasi, melalui komunikasi dan pertukaran barang dagangan pada wilayah-wilayah netral.
Pasar-pasar formal tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kekacauan, tidak ada jaminan keamanan. Namun desakan-desakan kebutuhan dan kekuatan ekonomi masyarakat menyebabkan mekanisme pasar terus berlangsung walaupun tidak dimediasi dalam bentuk wadah yang formal tetapi muncul dalam wajah tradisional dalam bentuk ”pasar kaget dan papalele” di berbagai tempat di pelosok kota Ambon. Bahkan di daerah-daerah perbatasan pemukiman masyarakat Kristen dan Islam aktifitas ”pasar kaget dan papalele” (serta para supir pengangkut barang dagangan) semakin bertambah. Memang selain desakan ekonomi masyarakat yang begitu kuat, kehadiran ”pasar kaget dan papalele”[4] ini juga dilatarbelakangi oleh rasa takut dan curiga masyarakat yang cukup tinggi kepada komunitas yang lain.[5] Dan harus diakui bahwa situasi yang tidak aman yang ditambah dengan ketakutan serta kecurigaan bisa menjadi lahan subur untuk bertumbuhnya manipulasi harga dari para pedagang terhadap pembelinya. Bahkan proses tawar-menawar yang tidak rasional pun antara penjual dan pembeli sesunguhnya sangat rentan terhadap konflik.
Pasar Wahana Rekonsiliasi
Muncul dan bertahannya ”pasar kaget dan papalele” sebagai media ekonomi tradisional dalam menjawab tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat pada saat konflik berlangsung tidak hanya mengindikasikan adanya rasa takut dan tidak aman dalam masyarakat untuk melakukan aktifitas yang jauh dari lingkungannya. Tetapi lokasi pasar yang tersebar sampai di perbatasan antara dua komunitas sosial (Islam dan Kristen) dan langkah-langkah berani untuk mengambil resiko yang dilakukan oleh papalele ketika berjualan di lokasi yang mayoritas berbeda agama darinya juga mengindikasikan adanya rasa percaya yang muncul di awal dan dalam setiap perjumpaan yang terjadi. Rasa percaya ini kemungkinan juga lahir karena para pedagang atau pelaku pasar tersebut adalah orang-orang yang menerapkan bisnis yang benar dan tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga memiliki orientasi sosial. Maksudnya orientasi bisnis dewasa ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar tetapi juga memiliki manfaat sosial bagi masyarakat (kesejahteraan) dan dunia (kelestarian ekonsistem dan penegakan nilai-nilai kebenaran serta keadilan). Bahkan upaya untuk mencari keuntungan yang besar dan tidak diimbangi dengan kualitas produk serta dampak sosial yang baik tidak akan melangengkan usaha tersebut.
Aktivitas yang dilakukan kelompok kepentingan ekonomi, pada satu sisi dapat dilihat sebagai murni motif ekonomi, dimana kondisi seperti disebutkan merupakan peluang yang baik bagi mereka untuk meraih keuntungan yang besar dari hasil jualannya. Tetapi pada sisi yang lain, tanpa disadari oleh mereka maupun kebanyakan orang, inisiatif mereka untuk berkomunikasi dan berjumpa (bakudapa) satu dengan yang lainnya dalam kondisi yang penuh resiko ini telah turut membantu mencairkan perlahan-lahan kebekuan dan kemacetan akibat konflik. Komunikasi dan perjumpaan mereka dapat dilihat sebagai point penting untuk proses dialog dan upaya perdamaian Ambon. Alasannya, pertama, melalui perjumpaan dan komunikasi, kecurigaan dan pandangan negatif oleh masing-masing orang atau kelompok berangsur-angsur hilang dan mulai terbangun sikap saling percaya, minimal di antara para distributor atau sesama penjual. Kedua, melalui perjumpaan dan sikap saling percaya, masing-masing orang sadar ataukah tidak, telah menyatakan kesediaan untuk mau saling mendengar dan belajar satu dengan yang lainnya.[6] Dengan demikian klaim-klaim pembelaan diri dan pembenaran diri dari kedua komunitas juga berangsur-angsur menghilang dari masyarakat.
Jadi proses perjumpaan yang terus-menerus terjadi inilah yang mengiring mereka untuk saling mengenal lebih jauh sehingga terbuka ruang untuk berbagi cerita tentang persoalan yang dihadapi bersama. Dengan kata lain, di pasar inilah dialog kehidupan itu terbangun sampai di komunitas yang paling bawah tanpa rekayasa pihak lain. Hal ini dengan sendirinya akan mengurangi rasa curiga dan takut di antara mereka serta lambat laun menimbulkan rasa percaya. Sehingga akhirnya muncul kesadaran akan saling membutuhkan ketimbang saling mempersalahkan antara komunitas. Inisiatif damai yang muncul dari dalam diri setiap pelaku pasar ini sesungguhnya adalah modal dasar bagi sebuah upaya damai yang lebih luas. Sebab tanpa inisiatif damai dari setiap individu, damai yang sejati itu hanya akan menjadi sesuatu yang semu.
Disisi lain, keberanian para pelaku pasar tersebut untuk menerobos kebekuan hubungan antara kedua komunitas sosial juga adalah sebuah langkah yang kreatif untuk mengalihkan perasaan trauma, takut, sedih, kecewa, bimbang dan keinginan untuk membalas atau melampiaskan rasa sakit hati kepada sesuatu yang lain, yang berangsur-angsur berfungsi sebagai sebuah terapi sosial untuk mengatasi kemelut hidup yang mereka hadapi. Bahwa keterbukaan tersebut adalah sebuah jalan keluar nonviolence yang mengalihkan dan menghilangkan perhatian mereka dari dua alternatif yang selama ini dipakai untuk menyelesaikan persoalan antara dua komunitas yaitu fight dan flight ’menyerang dan menghindar’ atau saling membalas kejahatan.
Lebih dari pada itu, rasa saling membutuhkan antara penjual dan pembeli akan membuat mereka untuk berhati-hati agar hubungan yang saling menguntungkan tersebut bisa berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama. Justru situasi konflik sedapat mungkin dihindari atau ditiadakan sama sekali sebab jika konflik terjadi maka secara otomatis aktifitas pasarpun akan tergangu dan hancur. Dimana barang-barang dagangan menjadi tidak laku dan ini berarti menimbulkan kerugian.
Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam pasar, ciri manusia sebagai mahluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain juga terjalin dengan indah. Dan menjadi pra kondisi bagi terciptanya rekonsiliasi di Ambon. Lewat interaksi di dalam pasar yang memunculkan hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak yang tadinya bertikai akhirnya mampu mencairkan ketegangan dan membuka proses ke arah perdamaian. Pasar yang merupakan tempat transaksi pertukaran kebutuhan hidup secara tidak sengaja justru mempercepat proses perdamaian di antara masyarakat Ambon. Dapat dikatakan juga bahwa masyarakat yang mau duduk bersama untuk berdagang di dalam pasar itu juga adalah mereka yang mulai belajar untuk keluar dari persoalan yang dihadapi dan memilih alternatif lain secara kreatif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kreatifitas ini juga membantu masyarakat untuk tidak tengelam atau berlarut-larut memikirkan konflik, rasa sakit hati, kemarahan, atau pembalasan dendam. Di sisi lain proses-proses memaafkan pun lambat laun akan terbentuk dan bahkan mungkin telah menjadi dasar dalam memulai komunikasi di pasar.
PASAR SEBAGAI SEBUAH REFLEKSI.
Pasar adalah wujud dari sebuah dialog kehidupan yang mempertemukan dua komunitas (Islam dan Kristen) yang tercerai-berai akibat konflik dalam sebuah interaksi ekonomi di Ambon. Kegiatan ekonomi ini merupakan ’salah satu’ cikal bakal lahir dan berseminya gerakan rekonsiliasi di Ambon. Dialog kehidupan ini merupakan sebuah budaya perdamaian non violence yang tumbuh di dalam masyarakat tanpa direkayasa oleh pihak pemerintah, alami, berbasis pada inspirasi masyarakat bawah, sangat inklusif dan sekaligus menjadi bukti bahwa ekonomi tidak hanya menjadi pemicu konflik tetapi juga menjadi ujung tombak penyatu kedua komunitas yang sementara bertikai (Kristen dan Islam) atau rekonsiliasi.
Pentingnya peranan pasar bagi sebuah aksi kemanusiaan mestinya menjadi perhatian berbagai pihak agar sarana ini tetap eksis. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pasar sering dilihat sebagai sesuatu yang kotor dan tidak bermoral. Namun kebaikan dan manfaat dari pasar pun tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahwa manusia adalah mahluk ekonomi dan juga mahluk sosial yang membutuhkan realisasi eksistensinya tersebut di tengah konteksnya.
DAFTAR PUSTAKA
Appleby R. Scott, The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation, Lanham: Rowman & Littlefield, 2000.
Belshaw Cyril S., Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern, Jakarta : Gramedia, 1981.
Herr Robert dan Judy Zimmerman-Herr (eds.), Transforming Violence (Scottdale dan Waterloo: Herald Press, 1998.
Piris Jhon, Tragedi Maluku : Sebuah Krisis Peradaban, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Rozi Syafuan dkk., Kekerasan Komunal : Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Yogyakarta, Jakarta : Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik – LIPI, 2006.
Rumahuru Y. Z., Peace and Dialogue : Kajian Sosiologi Terhadap Dialog dan Inisiatif Damai di Ambon 1999 – 2004, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2005.
Trijono Lambang (Ed.), Potret Retak Nusantara : Studi Kasus Terhadap Konflik di Indonesia, Yogyakarta : CSPS Books, 2004.
[1] Pasar kaget adalah suatu istilah yang baru muncul pada tahun 1999 atau setelah pertikaian di Ambon. Yang dimaksudkan adalah para penjual kontemporer yang selama konflik berinisiatif menjual kebutuhan pangan seadanya pada wilayah-wilayah pemukiman warga. Sejak tahun 2002 telah dilakukan lokalisasi oleh pemeritah kota Ambon pada lokasi pasar yang dibangun pemerintah, namun masih cenderung memotong pasar dengan berjualan pada pinggiran jalan dan pemukiman warga.
[2] Papalele adalah istilah di Ambon untuk menyebutkan pedagang kecil yang berjualan keliling membawa barang dagangannya berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Namun demikian dibedakan dari pedagang asongan di tempat lain. Umumnya papalele adalah orang yang membawa dan menjual hasil panen kebunnya sendiri seperti buah-buahan, sayuran dan jenis umbi-umbian, atau hasil tangkapan ikannya. Belakangan ini barang dagangan mereka sudah cukup variatif dan bisa saja dibeli dari tempat lain kemudian dijual kembali.
[3] Yang dimaksudkan dengan kelompok kepentingan ekonomi di sini adalah kelompok-kelompok masyarakat biasa yang karena tuntutan kebutuhan hidup (terutama makan) mengorganisir diri secara diam-diam untuk berkomunikasi dengan pihak lain di luar komunitasnya.
[4] Pasar kaget dan papalele yang dimaksudkan adalah pasar yang terjadi dalam lokasi masyarakat setempat.
[5] Bnd. Syafuan Rozi dkk, “Gagal dan Sukses Kelola Resolusi Konflik di Maluku Utara”, dalam Syafuan Rozi dkk, Kekerasan Komunal : Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Yogyakarta, Jakarta : Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik – LIPI, 2006, hal. 257.
[6] Pada hakikatnya dialog menghendaki adanya sikap sadar diri dan keterbukaan serta kesediaan untuk membangun sikap tulus.
-
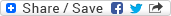
- Jemmy Talakua's blog
- Log in to post comments
- 556 reads