Pertanian Garam
Secercah Harapan dari Teknologi Ulir Filter
Oleh: Siwi Nurbiajanti/Rini Kustiasih 0 Komentar FacebookTwitter
INDONESIA sudah swasembada garam, meski baru untuk garam konsumsi. Produksi garam tradisional selama ini belum bisa masuk ke industri, karena kualitasnya rendah. Kini, dengan teknologi sederhana yang disebut geomembran atau ulir filter, ada harapan produktivitas garam naik, sekaligus kualitasnya memenuhi standar industri.
Abdus Somad (65), petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, optimistis bisa menaikkan harga garam olahannya dari yang biasanya Rp 150-Rp 200 per kilogram, kini menjadi Rp 350-Rp 400 per kg. Kejernihan dan kebersihan garam yang baik, serta kadar keasinan garam yang lebih tinggi membuat bapak lima anak itu tidak lagi minder menghadapi garam impor dari India dan Australia.
”Semuanya ini tanah titipan,” kata Somad sembari berjalan menunjukkan lahan garam yang berada tepat di belakang rumahnya, beberapa waktu lalu. Ke mana jari telunjuknya mengarah, di sanalah lahan titipan Ilahi yang dikelolanya. Sejauh cakrawala memandang, yang tampak ialah petak-petak tanah, kincir angin, pekerja yang memanggul karung-karung, dan kilat-kilat kristal garam berwarna putih. Somad menyebut luas lahannya sekitar 2 hektar (ha).
Berjalan agak ke tengah di lahan yang dikelolanya tersebut, 15 petak tanah yang dilapisi terpal warna biru menarik perhatian, karena berbeda dengan sebagian besar petak di sana yang berupa tanah.
Ukuran setiap petak berlapis terpal itu berkisar 37 meter x 8 meter sampai 40 meter x 8 meter. Hujan deras semalam sebelumnya mengakibatkan kristal-kristal garam yang terlihat di permukaan terpal itu masih terendam air. Aroma air garam yang amis menguar, namun dari sanalah Somad dan 10 anggota kelompok tani Garam Persada menggantungkan penghidupannya.
”Sisa air hujan mengakibatkan air berwarna kuning, dan garam belum semuanya jadi. Tetapi kalau hari ini panas seharian, sudah bisa langsung dipanen. Satu hektar (ha) bisa panen 100-120 ton per hari,” kata Somad.
Jumlah panen garam per hektar itu terbilang fantastis di Cirebon, mengingat rata-rata per hektar produksi garam di kawasan itu baru 80-90 ton. Petak-petak dilapisi terpal itulah yang menurut Somad membuat capaian produksinya naik. Selain itu, sistem ulir atau pengolahan garam menggunakan lahan peminihan atau filter berbentuk ulir, yang tanahnya dibuat beralur pendek-pendek, juga bagian dari mekanisme mengoptimalkan hasil kerja terpal itu.
Septi Ariyani (33), penyuluh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon menyebut teknologi penggaraman itu geomembran. Sistem peminihan dengan tanah beralur disebut teknik ulir. ”Penemunya adalah Pak Dradjat (57), instruktur penelitian di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal,” katanya, yang hari itu bersama rekan sesama penyuluh, Ibadullah Aziz (32), mendampingi Abdus Somad menantikan kedatangan Dradjad dari sebuah pertemuan di Tegal, Jateng.
Somad sudah dua tahun ini menggunakan teknologi ulir filter tersebut. Dalam beberapa kali panen, produksinya naik dibandingkan dengan rata-rata hasil panen sistem penggaraman tradisional. ”Garamnya juga lebih putih, padat, dan bobotnya berat. Garam lebih bersih karena tidak bercampur dengan tanah sehingga harganya bisa lebih tinggi,” tutur kakek 10 cucu ini.
Di seberang petak-petak berlapis terpal, adalah petak-petak tanah berair garam dengan jarak antarpetaknya sekitar 1,5 meter. Petak lebih kecil itu jika dilihat dari jarak jauh menyerupai ulir. Pada petak ulir inilah air garam dibiarkan menjadi tua, sehingga kadar salinitasnya naik sebelum dimasukkan ke dalam meja garam atau meja kristal, yakni petak berlapis terpal tadi.
Lebih baik
Dradjat yang tiba di Cirebon pada sore hari kemudian menerangkan, dalam teknologi ulir filter, air laut yang akan diolah menjadi garam dimasukkan ke petak penampungan berkedalaman 2 meter, dan dua kolam peminihan. Selanjutnya, air dialirkan ke kolam ulir atau kolam yang berkelok-kelok, yang berjumlah sekitar 100 kelokan, dengan jarak setiap kelokan 1 meter hingga 1,5 meter.
Pada setiap pintu ulir dipasang filter, yakni bahan campuran ijuk, batu ziolit, dan bathok arang, yang berfungsi mengendapkan partikel organik dan zat impurities, seperti magnesium, besi, timbal, bromida, dan tawas. Pada bagian bawah kolam ulir tanah dibuat tidak rata, sehingga proses pengendapan partikel organik dan impurities lebih sempurna.
Menurut Drajat, selama ini rata-rata tingkat kepekatan air laut di pantai utara sekitar 3 derajat BE (baume meter). Untuk bisa menghasilkan garam industri, derajat kepekatan air laut harus minimal 20 derajat BE.
Dari hasil percobaan, dengan mengolah air laut yang memiliki tingkat kepekatan 20 derajat BE, dihasilkan garam dengan NaCl sekitar 95 persen, yang bisa digunakan untuk industri es, kulit, dan tekstil. Sementara untuk bisa memenuhi kebutuhan industri pengeboran minyak dan farmasi, dibutuhkan garam dengan kandungan NaCl 97,4 persen hingga 99 persen. Untuk menghasilkan garam dengan kadar NaCl setinggi itu, dibutuhkan tingkat kepekatan air antara 25 derajat BE hingga 29,5 derajat BE.
”Dengan teknologi ulir filter, proses membuat air laut memiliki kepekatan tinggi atau oleh petani biasa disebut air tua, membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Air yang sudah difilter dari kolam ulir dialirkan menuju penampungan air tua, yang juga memiliki kedalaman 2 meter,” katanya.
Selanjutnya apabila tingkat kepekatan air sudah tinggi, air akan dialirkan ke lahan yang disebut meja kristal, dan dalam waktu 10 hari, sudah akan terbentuk kristal garam yang siap panen. Garam yang dihasilkan putih dan bersih, karena impurities mengendap sempurna. ”Jadi keseluruhan waktu yang dibutuhkan 24 hari,” kata Drajat.
Berbeda dengan metode konvensional yang selama ini biasa dilakukan oleh petani. Dengan metode konvensional, usia pengolahan garam mulai dari peminihan hingga menghasilkan kristal garam sekitar 28 hari. Karena lahan untuk peminihan pada metode konvensional merupakan lahan rata, impurities tidak bisa sempurna mengendap, sehingga warna garam cenderung kusam atau kehitam-hitaman.
Dengan metode konvensional, kadar NaCl garam biasanya juga dibawah 90 persen, karena tingkat kepekatan air saat dilepas ke meja kristal masih di bawah 20 derajat BE. Garam tersebut tidak bisa diterima untuk garam industri.
Intensifikasi
Kepala BPPP Tegal Heri Edy menuturkan, saat ini Indonesia sudah berswasembada garam, tetapi baru sebatas untuk garam konsumsi. Untuk garam industri, Indonesia masih mengimpor sekitar 2,3 juta ton per tahun (2013).
Untuk bisa memenuhi kebutuhan garam industri, lanjutnya, diperlukan lahan garam sekitar 28.000 ha, dengan asumsi rata-rata produksi mencapai 80 ton per ha. Padahal hingga saat ini, rata-rata produksi garam petani hanya sekitar 60 ton hingga 80 ton per ha.
Jika digabung dengan kebutuhan garam konsumsi, agar Indonesia benar-benar bisa menyetop impor garam, luas lahan garam yang harus tersedia di Indonesia setidaknya mencapai 44.705 ha.
Saat ini, luas lahan garam di Indonesia sekitar 29.367 ha, tersebar di beberapa wilayah, antara lain Madura, Rembang, Pati, Brebes, Cirebon, Indramayu, dan Karawang, serta pada 33 daerah penyangga (daerah yang masih ditumbuhkan), yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa.
Selain ekstensifikasi atau perluasan lahan garam, Heri berpendapat perlu upaya intensifikasi, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam. Salah satu upaya BPPP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah pengembangan teknologi ulir filter tersebut.
Dengan teknologi itu, produktivitas garam bisa mencapai 150 ton per ha. Kandungan Sodium Clorida (NaCl) pada garam juga mencapai lebih dari 94 persen, sehingga bisa memenuhi standar garam industri. Hal itu diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada garam impor.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010417289
-
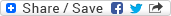
- Log in to post comments
- 499 reads