ANALISIS EKONOMI
Restrukturisasi Industri Kelautan
Ikon konten premium Cetak | 13 April 2015
Majalah The Economist (edisi 30/9/2004) menulis: ikan semakin langka, sementara ketamakan, kejahatan, kebencian, kebodohan, pengkhianatan, dan destruksi meningkat. Tidak tertutup kemungkinan ikan akan punah. Begitu majalah terkemuka ini menyitir buku Charles Clover berjudul The End of the Line: How Overfishing Is Changing the World and What We Eat. Buku ini menunjukkan, penangkapan ikan modern telah dilakukan secara brutal sehingga dunia terancam kelangkaan ikan.
RAD
Argumen ini mengingatkan kita pada artikel lugas Garrett Hardin, ”The Tragedy of Commons”, di jurnal Science pada 1968. Komoditas publik berisiko dieksploitasi secara masif. Saat rusak, tak satu pun merasa bertanggung jawab.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) membuat ilustrasi, eksploitasi ikan modern mirip dengan kegiatan di sektor pertambangan. Kemampuan menyedot sumber daya jauh lebih besar daripada kemampuan bumi menghasilkan sumber daya itu.
Dalam sektor perikanan domestik, nasib nelayan nyaris tak berubah dari waktu ke waktu. Upaya memaksimalkan hasil sering bertentangan dengan prinsip keberlangsungan ekosistem kelautan. Akibatnya, kebijakan menertibkan cara menangkap ikan sering ditentang para nelayan yang merasa dirugikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak selalu populer di kalangan nelayan.
Namun, di tengah kompleksitas persoalan, fokus pada upaya memperbaiki nasib nelayan dengan pendekatan sistematis dan profesional harus tetap diprioritaskan. Nasib nelayan tak akan berubah tanpa ada ”intervensi” yang bersifat struktural.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar nelayan (NTN), khususnya perikanan tangkap, turun 0,49 persen dari 106,72 pada Februari 2015 menjadi 106,20 pada Maret 2015. NTN adalah angka yang membandingkan harga yang diterima (indeks harga) dengan harga yang harus dibayarkan (indeks beli) nelayan. Indeks harga menunjukkan perubahan harga paket komoditas yang dihasilkan nelayan melalui penangkapan ikan. Sementara indeks beli menunjukkan perubahan harga paket komoditas yang harus dikeluarkan nelayan, baik untuk kepentingan hidup sehari-hari (konsumsi) maupun biaya melaut (produksi).
Penurunan NTN menunjukkan taraf hidup kelompok nelayan menurun. Jika dibandingkan dengan kelompok nelayan perikanan budidaya, penurunan pada nelayan tangkap lebih besar. Jadi, agendanya jelas, memperbaiki nasib nelayan tangkap melalui revitalisasi sektor kelautan secara menyeluruh, seperti yang dijanjikan pemerintah.
Presiden Joko Widodo saat dilantik menyampaikan pidato kemaritiman sebagai berikut, ”Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, serta memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ’Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya.”
Posisi Indonesia dalam peta perikanan dunia sangat strategis. Pertama, Indonesia salah satu pengekspor ikan terbesar dunia sehingga banyak negara bergantung pada kita. Kedua, pasokan ikan cukup besar mengingat Indonesia negara maritim. Kelemahannya, industri berbasis kelautan tak berkembang cukup baik.
Dengan teknik tradisional, nelayan tak mampu meningkatkan tangkapan. Sementara untuk meningkatkan teknik produksi, diperlukan akses permodalan. Sejauh ini bank enggan memberikan kredit karena tak ada jaminan bisa meningkatkan produksi. Modal dari bank justru digunakan menutup kekurangan kebutuhan hidup sehingga berpotensi tak kembali.
Salah satu upaya penting membangkitkan sektor kelautan adalah membangun basis industri berikut mata rantainya, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ekspor. Namun, setiap lini punya masalah yang pelik. Tanpa upaya merestrukturisasi basis industri di semua lini, sulit membangkitkan sektor kelautan dan meningkatkan taraf hidup nelayan.
Industri pengolahan ikan tak berkembang karena pasokan bahan baku ikan terbatas skala industrinya. Pasokan juga cenderung tak stabil. Untuk memacu industri pengolahan, bahan baku harus diimpor. Padahal, sangat mungkin ikan itu ditangkap dari laut kita, baik legal maupun ilegal. Begitu pula dengan industri pengalengan, bahan baku utamanya masih impor sehingga mahal. Pendek kata, guna memenuhi konsumsi dalam negeri saja, lebih murah impor ketimbang memproduksi sendiri.
Sungguh ironis mengingat sektor perikanan (bersama sektor pertanian) menyerap tenaga kerja paling besar, sekitar 35 persen dari total tenaga kerja. Namun, kinerjanya sangat menyedihkan. Sudah saatnya pemerintah merevitalisasi lintas kementerian yang esensinya mengaitkan sektor kelautan dengan mata rantai industri lain yang panjang. Jelas, diperlukan strategi industrialisasi sektor kelautan.
Membangkitkan sektor kelautan tak cukup sekadar meledakkan kapal pencuri ikan. Harus ada kerangka kebijakan industri maritim yang kuat. Menteri Kelautan dan Perikanan harus dibantu Menteri Perindustrian dan kementerian teknis lainnya. Peran Menteri Koordinator Kemaritiman menjadi sangat penting.
A Prasetyantoko, Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unika Atma Jaya, Jakarta
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/04/13/Restrukturisasi-Industri-Kelautan
-
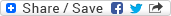
- Log in to post comments
- 753 reads