
Oleh Ahmad Arif
Sebagai keluarga ata, keluarga Kahumbu Nganji (50) telah turun-temurun melayani keluarga Kepala Desa Meuramba, Balla Nggiku (60). Namun, baru-baru ini, Kahumbu merasa mendapat kehormatan karena dipilih sebagai anggota staf di kantor desa.
Sebagai keluarga ata, keluarga Kahumbu Nganji (50) telah turun-temurun melayani keluarga Kepala Desa Meuramba, Balla Nggiku (60). Beberapa anak Kahumbu kini melayani anak Balla. Namun, baru-baru ini, Kahumbu merasa mendapat kehormatan karena dipilih sebagai anggota staf di kantor desa sekalipun posisinya hanya sebagai pesuruh.
Sebagai pesuruh Desa Meurumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dia digaji Rp 500.000. Bukan besaran gaji itu yang membuatnya bangga, melainkan seragam dinas dan status sosialnya. Sekalipun hari Sabtu (22/6/2019), dia tetap memakai seragam coklatnya.
Dia menjadi satu-satunya anggota staf desa yang berseragam. Tugasnya pagi itu untuk menyediakan minuman bagi peserta rapat desa dilakukan tanpa suara. Setelah mengangsurkan semua gelas minuman keramik untuk para peserta rapat, Kahumbu baru mengambil tempat duduknya sendiri.
”Ini kebanggaan besar bagi keluarga kami. Dulu tidak mungkin kami bisa punya posisi dan seragam staf desa, apalagi boleh ikut rapat desa,” ujar Kahumbu dengan mata berkaca-kaca.
Dalam budaya Sumba, masyarakat dibagi dalam tiga kasta berdasarkan keturunannya, yaitu kaum maramba atau bangsawan, kalangan kabihu atau orang bebas, dan golongan terbawah ata. Kalangan ata ini secara sosial ekonomi menjadi hamba atau budak bagi kalangan maramba. Di masa lalu, ata bisa menjadi persembahan serta diperjualbelikan atau ditukar dengan ternak.
”Saya tidak pernah sekolah karena harus jaga ternak,” kata Kahumbu. Sejak umur sepuluh tahun, dia sudah diberi tanggung jawab menjaga 60 sapi milik tuannya. ”Tak boleh ada ternak yang lapar, apalagi mati. Ayah Pak Kades dulu sangat keras. Kalau salah sedikit, kami pasti dipukuli.”
Balla Nggiku menambahkan, sebagaimana layaknya bangsawan lama di Sumba, ayahnya memang keras kepada para ”orang dalam rumah”, sebutan halus untuk ata. Bukan hanya kekerasan fisik, mereka juga tidak dihargai. ”Mereka juga biasanya dilarang sekolah. Kalaupun sekolah, paling sampai sekolah dasar karena kalangan maramba tak ingin tersaingi ata-nya,” ujarnya.
Namun, Balla berpikir sebaliknya. Semenjak orangtuanya meninggal, Balla yang mewarisi 30 keluarga ata membuat perubahan. Anak-anak ata diberinya keleluasaan untuk bersekolah dan bekerja, termasuk anak Kahumbu yang rata-rata sudah tamat sekolah menengah atas. ”Saya percaya, mereka punya hak sama sebagai warga negara,” katanya.
Jika kalangan ata mereka sukses dan mandiri, hal itu juga meringankan tanggung jawab maramba. ”Nyatanya, setelah sukses, mereka tetap masih berhubungan baik dengan kami. Setiap diminta membantu upacara adat, mereka datang,” kata Balla.
Antropolog University of Southern California, AS, Janet Hoskins (2004), menulis, relasi ata dan maramba merupakan praktik perbudakan di era modern. Fenomena ini telah berlangsung sangat lama dan memuncak pada era kolonial Belanda. ”Sumba sebelumnya dikenal ’Pulau Cendana’ oleh orang Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Namun, di abad ke-18 dan ke-19, kayu-kayu habis dan ekspor dari pulau ini digantikan barang hidup: kuda-kuda, kerbau, dan budak manusia, yang lalu ditukar dengan emas, baja, dan senjata.”
Di abad ke-18 dan ke-19, kayu-kayu habis dan ekspor dari pulau ini digantikan barang hidup: kuda-kuda, kerbau, dan budak manusia, yang lalu ditukar dengan emas, baja, dan senjata.
Saat melakukan studinya di Sumba Timur pada tahun 1988, Hoskins masih melihat penyerahan seorang ata dalam ritual penguburan Raja Kapunduk. Dalam upacara itu, Hoskins dikejutkan oleh kedatangan utusan dari Desa Wunga yang membawa gadis muda usia 19 tahun sebagai persembahan kepada keluarga yang meninggal. ”Perempuan muda itu budak atau yang biasa disebut tou uma dalo (orang dalam rumah),” ujar Hoskins.
Ade Siti Barokah dalam tesisnya di Erasmus University, Belanda (2016), menulis, masih berlangsungnya praktik perbudakan di Sumba Timur hingga saat ini disebabkan keterikatan yang kuat dengan simbol budaya mereka. Ideologi hegemonik yang percaya pada ”kemurnian darah” dan kebesaran maramba terus diproduksi, dipraktikkan, dan dipertahankan. Terlebih lagi institusi lokal, termasuk peraturan dan regulasi, pembagian peran, dan sanksi sosial, memaksa masyarakat untuk mematuhi tradisi mereka.
Tidak semua wilayah Sumba masih melestarikan tradisi perbudakan ini. ”Hanya di Sumba Timur yang masih kuat tradisi ini. Di Desa Meuramba saja ada sekitar 30 persen penduduk dari kalangan ata dan rata-rata mereka masih harus bekerja untuk maramba-nya. Di desa-desa lain kemungkinan jumlahnya sama, bisa lebih,” kata Balla.
Peluang perubahan
”Terlalu banyak kisah sedih tentang ata,” ucap Lai Ria (31), maramba dari Desa Mauramba, Kecamatan Kahaungu Eti, yang menjadi pendamping Program Peduli Kemitraan untuk Desa Meurumba dan Mauramba. Akan tetapi, kebanyakan tragedi itu tak tersentuh hukum positif negara karena hal ini kerap terbungkus budaya atau tradisi.
Dia mencontohkan kisah anak ata yang meninggal karena dipukul maramba-nya. Namun, ibu kandungnya, yang juga ata, diminta mengakui sebagai pelaku pemukulan itu sehingga harus menjalani hukuman penjara.
Keluarga Lai merupakan salah satu pelopor yang membawa perubahan dengan membebaskan semua anak ata sekolah. Dia mengatakan, salah satu anak ata yang seumuran dengannya kini telah menjadi tentara dan bertugas di Jawa. ”Dulu, kami sekolah bareng, tiap hari tugasnya membawa bekal makanan saya. Dia satu-satunya tentara dari kalangan ata di daerah sini,” katanya.
Sekalipun sudah menjadi tentara dan tinggal di luar Jawa, hubungannya dengan keluarga Lai tetap terjalin. Saat Lai hendak menikah, sang tentara mengirim sejumlah uang untuk membantu biaya ritual adat. ”Adat dan hubungan tidak harus rusak dengan memberikan hak-hak dasar ata,” kata Lai.
Menurut Stepanus L Paranggi, juga dari Program Peduli Kemitraan, upaya perubahan yang dilakukan selama ini adalah dengan menggugah kesadaran dari para maramba agar memberikan hak-hak dasar kepada kalangan ata. ”Sejauh ini baru bisa kami lakukan di desa-desa yang tokoh desanya mau terbuka,” kata Stepanus.
Selama ini, menurut dia, banyak kalangan ata yang belum mendapatkan identitas kependudukan dan ini yang membuat mereka kerap tak terlayani hak-hak dasarnya, seperti pendidikan dan kesehatan. ”Terutama yang paling rentan adalah para perempuan ata yang tidak punya suami dan anak-anaknya. Banyak perempuan ata yang melahirkan anak-anak maramba-nya, namun tidak memiliki status sebagai istri sah. Program kami mendorong desa agar memperbaiki pendataannya dan sejauh ini baru bisa kami lakukan di dua desa,” tuturnya.
Desa Meurumba dan Mauramba kini telah memberikan identitas kepada semua warganya tak terkecuali. Mereka yang selama ini tak terdata mulai mendapatkan perhatian. ”Sudah ada tujuh kepala keluarga perempuan yang mendapat bantuan ternak kuda induk. Semua warga desa harus mendapat hak yang sama,” kata Balla.
Manajer Program Peduli Kemitraan Yasir Sani mengapresiasi perubahan yang terjadi di Desa Meurumba. Desa ini merupakan salah satu dampingan Kemitraan bersama Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) sejak tahun 2015 untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat adat dan terpencil. ”Kami harap pemerintah daerah bisa turut berperan sehingga perubahan bisa juga terjadi di desa-desa lain. Seperti kita ketahui, praktik kasta sosial ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia,” katanya
Selain itu, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 yang menegaskan setiap warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, dan bebas dalam hati dan pikiran. Praktik ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan para tokoh bangsa kita sejak 1945 adalah untuk semua warga. Semestinya praktik perbudakan ini tak boleh lagi ada di negeri ini, apa pun alasannya….
-
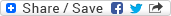
- Log in to post comments