Di luar Konvensi 1951, melindungi pengungsi perubahan iklim di Pasifik
Reporter: Elisabeth Giay
Oleh Ian Fry
Tidak diakui oleh komunitas global sebagai ‘refugees’ atau ‘pengungsi’, mereka yang terbengkalai karena bencana-bencana alam akibat perubahan iklim, tidak mungkin menerima perlindungan hukum yang pantas.
Pada 2013, Ioane Teitiota dari Kiribati, meminta Pengadilan Tinggi Selandia Baru untuk mengabulkan banding yang ia ajukan, terhadap keputusan Pengadilan Tribunal Imigrasi dan Pengawal Perbatasan. Permohonan Teitiota, yang mencari suaka sebagai pengungsi perubahan iklim, telah ditolak oleh badan imigrasi negara itu.
Tribunal itu menemukan bahwa Teitiota telah melakukan apa yang mereka sebut sebagai migrasi sukarela yang adaptif atau ‘voluntary adaptive migration’, dan bahwa keputusannya untuk migrasi ke Selandia Baru tidak dapat dilihat sebagai langkah yang ‘terpaksa’.
Teitiota mengajukan banding atas penolakan ini dan proses bandingnya berakhir di Mahkamah Agung Selandia Baru. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi negara itu telah mengemukakan bahwa, sehubungan dengan Konvensi Terkait Status Pengungsi atau Refugee Convention, Teitiota dianggap tidak menghadapi ancaman bahaya yang genting, dan lebih lanjut, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Pemerintah Kiribati itu, gagal memberikan bantuan dan dukungan kepada warganya untuk menghadapi dampak kerusakan lingkungan dan alam.
Kasus Teitiota ini bukan kasus pertama dimana seseorang menyatakan dirinya sebagai pengungsi akibat perubahan iklim, dan kasus ini juga tidak mungkin menjadi kasus yang terakhir.
Tidak lama setelah Jacinda Ardern terpilih sebagai Perdana Menteri Selandia Baru pada tahun 2017, Menteri Perubahan Iklim, James Shaw, mengumumkan bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan membuat kategori visa, untuk membantu memindahkan orang-orang Pasifik yang terlantar akibat dampak perubahan iklim.
Namun pada Februari tahun ini, Wakil Perdana Menteri, Winston Peters mundur, ia berkata masih terlalu dini untuk membuka kewarganegaraan Selandia Baru, bagi para pengungsi lingkungan hidup yang menyelamatkan diri mereka dari dampak perubahan iklim.
Ada beberapa pengamatan dapat diambil dari kisah perjuangan ‘pengungsi perubahan iklim’ Selandia Baru. Walaupun jumlah data yang menunjukkan, secara ilmiah, bahwa naiknya permukaan air laut saat ini yang menimbulkan permasalahan akibat perpindahan pengungsi itu terbatas, siklon-siklon tropis yang baru-baru ini menyerang wilayah Pasifik – dampak dari pemanasan suhu bumi – adalah masalah yang berbeda.
Badai tropis besar yang terbentuk dalam beberapa tahun terakhir ini, Siklon Pam dan Siklon Winston – sebagai dua contohnya – telah menyebabkan perpindahan dalam negeri oleh penduduk-penduduk desa di sejumlah negara. Di Tuvalu, contohnya, naiknya pasir ke darat dari lautan di tiga pulau kecil akibat gelombang badai yang disebabkan oleh Siklon Pam, memaksa masyarakat setempat untuk pindah ke Funafuti.
Memang, kelihatannya, hanya sedikit informasi yang ada untuk dapat menentukan apakah bencana-bencana siklon ini yang menyebabkan migrasi lintas batas di Pasifik. Meskipun demikian, ancaman ini sangat nyata dan semakin genting karena naiknya jumlah ancaman yang disebabkan oleh perubahan iklim.
Sementara banyak orang yang mengungsi melintasi batas internasional sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa alam terkait iklim, tampak jelas bahwa mereka tidak dapat didefinisikan sebagai pengungsi di bawah Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.
Menurut definisinya, ‘pengungsi’, sekelompok orang Pasifik ini tidak dapat dimasukkan, karena mereka belum mengalami suatu bentuk ketakutan yang beralasan akan penganiayaan. Akibatnya, orang-orang yang terpaksa pindah dan terlantar akibat perubahan iklim ini, cenderung tidak mendapatkan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh Konvensi Pengungsi tersebut.
Sebagai akibat dari kurangnya perlindungan hukum ini, Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga mengumumkan, pada KTT Kemanusiaan Dunia atau World Humanitarian Summit tahun 2016, bahwa Tuvalu akan mengajukan sebuah resolusi kepada Majelis Umum PBB, untuk mulai bekerja dan mengembangkan rezim hukum yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, akibat dampak perubahan iklim. Draf resolusi itu saat ini sedang diedarkan, sebelum nantinya akan dipertimbangkan di Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.
Dengan membuat pengumuman ini, PM Sopoaga dengan jelas menegaskan bahwa resolusi ini merupakan tanggapan terhadap suatu masalah global, dan bahwa ini bukan penanda bahwa warga Tuvalu ingin pindah ke negara lain. Orang-orang Tuvalu, tegasnya, ingin tetap tinggal di Tuvalu.
Pandangan bahwa migrasi akibat perubahan iklim adalah strategi adaptasi, dan bukan suatu keharusan yang dipaksakan, didukung oleh mantan Presiden Kiribati, Anote Tong, ketika ia merujuk pada konsep bermigrasi dengan bermartabat, ‘migration with dignity’.
Mantan presiden itu menganggap migrasi sebagai strategi adaptasi, dan ingin memastikan bahwa siapa pun dari Kiribati yang ingin bermigrasi ke luar negeri, harus dapat melakukannya tanpa menjadi warga negara kelas dua di negara lain. Sebagai bagian dari kebijakan ini, Pemerintah Tong telah membeli tanah seluas 5.500 hektare di Fiji.
Opini Anote Tong ini tidak dipegang oleh Presiden Kiribati saat ini, Taneti Mamau, yang lebih memilih kebijakan untuk bertahan dan melawan, ‘stay and fight’ – sejalan dengan pandangan PM Sopoaga. Meskipun demikian, Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, dalam pertemuan perubahan iklim pada 2017 telah mengumumkan, bahwa ia akan membiarkan masyarakat Kiribati dan Tuvalu untuk menetap di negaranya.
Beberapa komunitas di Kepulauan Pasifik cenderung menganggap perubahan iklim sebagai ancaman bagi mata pencaharian mereka, dan mungkin lebih memilih untuk bermigrasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa yang lainnya akan terpaksa pindah secara global karena dampak perubahan iklim.
Meskipun mereka mungkin tidak masuk dalam definisi pengungsi, tapi sebagai pengungsi perubahan iklim, mereka harus tetap diberikan hak yang layak di negara tempat tinggal mereka yang baru, dan kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka jika keadaan berubah. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan dunia mulai saat ini, adalah kerangka kerja hukum dan kebijakan yang kuat untuk mendukungnya. (PINA/Policy Forum)
Ian Fry adalah pakar dalam hukum dan kebijakan lingkungan hidup internasional.
Editor: Kristianto Galuwo
-
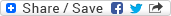
- Log in to post comments