Dua pelepah sagu jadi latar panggung pertunjukan. Enam pemain berdiri sejajar di belakang tifa, menabuh dalam irama teratur. Dua pemusik sesekali meniupkan fuu atau triton.
Fuu adalah alat musik terbuat dari kerang dimainkan dengan meniup. Di bagian depan, dua pemain lain duduk memainkan stembas dan piko. Piko adalah alat musik tarik dari Pegunungan Tengah Papua.
Di awal pertunjukan, para pemain hanya memainkan alat-alat musik tradisional Papua ini sambil mengucapkan,” saguuuu…saguuuuuu….”
Tak lama kemudian, Septina Rosalina Layan beralih dari tifa ke piano yang diletakkan di sudut panggung.
Seorang pemain lain muncul dari arah penonton dengan suara menyerupai ratapan dan menuju panggung. Tak lama teriakan sagu dan sawit bergantian.
“Saguuuuu….sawittttt….saguuuu….sawitttttt….”
Musik tradisional dan modern dipadukan. Di layar tampak gambar pohon sagu dan sawit, hutan habis ditebang. Wajah anak-anak kehilangan tempat bermain. Para pemilik kehilangan dusun sagu, mobil pengangkut dan pekerja sawit.
Pertunjukan ini diakhiri tangisan. Satu persatu pemain menuju bagian depan panggung, duduk dan meratap.
“Kanaiwa kasasodla, kanaiwa awighre, bekai kanaiwa kawihe…” Ini sebuah lirik dalam bahasa Marind, berarti,’ “kami sedih, kami gelisah, hati kami menangis…”
Sagu (Da’) vs Sawit, begitu judul pertunjukan musik karya seniman Septina Rosalia Layan ini. Ia kombinasi beberapa alat musik baik yang khas Papua maupun modern.
Karya ini berlatar belakang pengalaman sang seniman di tanah kelahirannya, Merauke, Papua. Daerah ini makin banyak perkebunan sawit dan menggusur hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat.
Pohon sagu sebagai makanan pokok makin sulit dicari, kini berganti sawit. Dalam karya ini, sagu tak hanya diterjemahkan sebagai makanan pokok juga identitas budaya orang Papua yang pelan-pelan tergerus sawit dan berbagai budaya baru yang datang bersamanya.
“Karya ini lahir dari hati saya. Saya lahir besar di Merauke. Banyak sekali perusahaan sawit masuk,” kata Septina usai pertunjukan.
Perjumpaan dengan Sem Silas Ndiken, salah seorang pemilik dusun dari keturunan Bigai ikut menginspirasi karya ini.
“Seandainya saya satu-satunya Bigai, saya tak akan kasi tanah ini (ke perusahaan),” katanya menirukan pernyataan Sem Silas.
Pro dan kontra di tengah masyarakat antara menerima perusahaan atau mempertahankan tanah adalah realitas sehari-hari masyarakat seperti di Merauke. Janji-janji perusahaan terkadang membuat warga rela melepaskan tanah ke perusahaan. Ada juga gigih menolak.
Septiana ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa penting mempertahankan sagu dan berbagai identitas budaya Papua, lewat karya ini.
Pertunjukan musik ini terbagi dalam tiga bagian. Pertama, menunjukkan kegelisahan dan kekecewaan atas sagu yang hilang. Ia sebagai simbol perebutan lahan makan dan perubahan budaya masyarakat Papua.
Kedua, menampilkan peperangan tanpa jawaban akhir “sagu atau sawit…” Ketiga, menampilkan penyesalan, pertanyaan, kekhawatiran, ratapan kesedihan, doa dan harapan.
Septina tampil bersama para mahasiswa dan dosen dari Insitut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, tempat dia mengajar kini.
Untuk pertunjukan ini, mereka mempersiapkan kurang lebih tiga minggu. Pertunjukan musik ini akan dipentaskan di wilayah-wilayah dimana ekspansi perusahaan sawit menggila seperti Merauke, Keerom dan beberapa wilayah lain di Papua.
Semua tim dalam pertunjukan ini senang berpartisipasi dalam karya Septina, seperti Alfred Mofu, yang berperan menabuh tifa dan meniup triton.
“Ini motivasi bagi semua untuk melihat lebih dalam situasi di Papua dan bersuara lewat karya.”
Hal sama dikatakan Carolina Wanggai, menabuh tifa dan mengisi suara. “Saya bangga ikut tampil. Kita bisa menyampaikan kepada penonton, makanan pokok kita itu sagu.”
Apresiasi atas karya ini disampaikan para penonton. Yuliana Langowuyo, Direktur Sekretariat untuk Keadilan, Perdamaikan dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, mengatakan, karya ini alternatif lain kampanye melawan sawit.
“Laporan dampak kehadiran sawit ini sudah dibuat, tebal dan orang cape baca, lewat karya seni begini, penonton bisa langsung menangkap pesan. Ini gaya baru kampanye tolak sawit,” katanya.
Charles Toto, Chef dari Papua Papua Jungle Chef Community juga mengapresiasi karya ini. Dia memberikan masukan antara lain perlu memasukkan filosofi sagu karena belum terlihat dalam karya ini.
Sagu, katanya, sangat berharga bagi kehidupan orang Papua baik untuk makanan, pakaian maupun sebagai bahan membuat rumah.
I Wayan Rai, Rektor ISBI Tanah Papua menyatakan, karya ini contoh pengembangan musik baru kontemporer berbasis tradisi. Dalam bidang seni dan budaya, katanya, banyak potensi di Papua.
“Semoga ke depan makin banyak dukungan kepada anak muda Papua untuk menggali kreativitas seperti dilakukan Septina bersama tim lewat karya Sagu (Da’) vs Sawit.”
Septina dengan karya Sagu (Da’) vs Sawit merupakan peraih hibah cipta perempuan kelola. Yayasan Kelola, pemberi hibah ini berikan perhatian khusus berupa peluang belajar, akses pendanaan, informasi bagi seniman, praktisi dan pelaku seni di Indonesia.
Di Jayapura, Septina bersama tim tampil dua hari di Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Wamena pada 6-7 Juni 2017.
“Saya seniman. Saya hanya bisa berbicara melalui karya. Semoga karya ini menjadi isnpirasi untuk siapapun yang bekerja untuk penyelamatan lingkungan dan budaya. Jangan pernah bosan walaupun kadang seperti tidak mengubah apapun, tapi kita harus terus melakukan.“
http://www.mongabay.co.id/2017/06/09/sagu-da-vs-sawit-begini-aksi-seniman-papua-melawan-sawit/
-
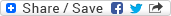
- Log in to post comments
- 332 reads