KOLOM POLITIK
Matahari Terbit dari Papua
M Subhan SD
25 Juli 2015
Tanah Papua tanah yang kaya
surga kecil jatuh ke bumi
seluas tanah sebanyak batu
adalah harta harapan
Papua selalu tampak indah dan penuh pesona. Lagu ”Aku Papua” karya Franky Sahilatua yang liriknya digarap bersama Robby Rumbiak, Wilson Wanda, Melky Lakalena, dan dipopulerkan penyanyi Edo Kondologit itu terasa sangat pas. Untaian pulau-pulau di Raja Ampat dengan laut nan biru menjadi daya tarik luar biasa. Pegunungan Jayawijaya yang berselimut salju abadi di daerah tropis sangatlah unik. Indigenous people-nya yang mendiami Lembah Baliem dan sekitarnya adalah potret keaslian Papua. Kekayaan hayati yang endemik seperti burung cenderawasih atau kanguru pohon menjadi gudang ilmu pengetahuan. Hutannya, sebagaimana seluruh hutan negeri ini, menjadi paru- paru dunia. Ukiran suku Asmat dan Kamoro, misalnya, memperlihatkan karya sarat makna dan bernilai tinggi. Dan, jauh di dalam perut buminya tersimpan emas sebagai sumber kehidupan.
Namun, di antara belantara dan perut buminya juga tersimpan magma yang setiap saat bisa membuncah ke permukaan. Konflik rasanya terlalu identik dengan Papua. Konflik suku hingga gerakan kemerdekaan, begitu sering terdengar di telinga. Dan, insiden Tolikara pada 17 Juli 2015 adalah salah satu buncahan magma itu. Aksi pembakaran 68 kios usaha dan sebuah mushala di Karubaga, yang terjadi tepat pada Idul Fitri 1436 Hijriah itu membuat hati pilu. Sebuah tindakan yang kontradiktif dengan makna Idul Fitri yang menyemai keluasan hati (saling memaafkan) dan persaudaraan (silaturahim). Ketika semuanya hangus terbakar, sesal kemudian sungguh tiada guna. Bukan hanya bentuk fisik yang rusak, kohesi sosial pun melemah dan kecurigaan menguat. Inilah sifat destruktif suatu konflik, terlebih lagi konflik berlatar agama.
Insiden Tolikara tampaknya menjadi fakta baru bahwa konflik di Papua tidak melulu berlatar politik-ekonomi, yaitu tuntutan kemerdekaan dan rivalitas pendatang dan penduduk asli akibat ketimpangan ekonomi atau konflik suku. Barangkali, setidaknya sejak era reformasi, baru kali ini konflik berlatar agama meletup di Papua. Jika benar ada konflik berlatar agama, tentu tidak bisa dianggap sepele. Jika menyangkut agama, akan semakin menambah ruwet permasalahan.
Sebab, agama merupakan sistem kepercayaan, yang punya aturan-aturan ketat, menjunjung moralitas, dan kepatuhan. Agama adalah institusi kebenaran (the body of truth), hukum (law), dan ritual (rites) di mana manusia tunduk pada kekuatan transenden (Adeniyi, 1993). Artinya agama terdiri norma-norma, aturan, perilaku, proses, atau struktur yang berorientasi pada kekuatan supranatural (Tuhan) dan harus ditaati oleh umat yang meyakininya.
Jika agama berkelindan dengan konflik-konflik lain yang laten di Papua, kepelikan masalahnya akan berlipat-lipat. Apalagi pelabelan kerap ditubuhkan ke dalam etnis dan agama tertentu, semisal Papua-Kristen, Bali-Hindu, Aceh-Islam. Apabila pelabelan itu menguat ditambah lagi dengan politisasi sentimen etno-religius, tragedi besar berada di depan mata. Nigeria adalah contoh konkret. Di negara yang bertepi di Lautan Atlantik itu terdapat sekitar 250 etnis. Namun, ada tiga etnis mayoritas, yaitu Hausa/Fulani (Muslim) di wilayah utara, Igbo (Kristen) di timur, Yoruba (dua agama banyak pemeluknya) di wilayah selatan dan barat.
Realitanya masyarakat pun terkotak-kotak dalam mayoritas-minoritas. Di wilayah utara, koneksi mayoritas-minoritas didasarkan pada agama, tetapi di wilayah selatan mayoritas-minoritas didasarkan pada etnis. Etnis yang mayoritas mendominasi, sedangkan etnis minoritas teralienasi. Agama ataupun etnis sama-sama menjadi identitas. Dalam sejarahnya, sejak era 1980-an, konflik di Nigeria berlangsung sangat panjang dan beregenerasi. Di Nigeria, konflik berlatar etno-religius telah membawa negara itu terpuruk jauh ke dasar jurang.
Di tengah masyarakat yang multietnis dan multikultur, konflik hampir selalu mencari momen tepat untuk menyulut api. Kemajemukan agama (religious plurality) dan diferensiasi etnis memang berpotensi membangkitkan konflik di masyarakat. Tinggal dipantik oleh faktor pemicu (trigger factor), apa pun juga, ”api” bisa menyala. Pengalaman negeri ini sudah lelah didera banyak konflik: Sambas, Sampit, Ambon, Poso, Maluku Utara, Papua, dan daerah-daerah lain. Belum lagi konflik politik karena terlalu banyak orang rebutan kursi kekuasaan.
Karena itu, insiden Tolikara harus dituntaskan. Bukan saja terkait langsung dengan peristiwanya, melainkan juga adalah resolusi konflik secara komprehensif, terutama membangun pemahaman bersama bahwa toleransi dan persatuan adalah ikatan hidup bangsa ini. Jika selama ini terlalu banyak keributan di pusat kekuasaan di Jakarta, saatnya berhenti dan beralih memikirkan wilayah-wilayah lain. Perlakuan diskriminatif terhadap daerah-daerah yang berlangsung sejak rezim otoriter di masa lampau telah melahirkan kecemburuan, kekecewaan, dan frustrasi. Inilah yang bisa menjadi benih-benih pemicu konflik.
Sayang, jika kita abai apalagi ada pembiaran. Tiba-tiba ingin merasakan dinginnya angin Kurima di Wamena yang bertiup pada sore sampai malam, agar bisa menyejukkan kondisi yang panas. Pagi hari, kita selalu melihat matahari terbit lebih dulu di Papua. Kehidupan pun dimulai dari ”surga kecil yang jatuh ke bumi”.
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/07/25/Matahari-Terbit-dari-Papua
-
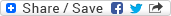
- Log in to post comments
- 162 reads