Perempuan dan Langkah Afirmatif
Oleh: Lies Marcoes
SECARA normatif, tindakan khusus sementara (affirmative action) untuk menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di ruang publik adalah niscaya.
Niscaya karena hanya dengan cara itu kepentingan perempuan yang dirundingkan dan diambil melalui keputusan-keputusan demokratis bisa disuarakan. Niscaya karena jika hanya ”dititipkan” kepada pihak lain (lelaki) kepentingan itu bisa bias (membelok) atau bahkan menguap. Langkah afirmatif dengan mengambil gagasan UNDP yang mensyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan merupakan aksi paling moderat dari mandat konvensi CEDAW. Ini konvensi yang memastikan tak ada diskriminasi terhadap perempuan berbasis prasangka jender. Sejumlah besar negara yang ikut menandatangani konvensi ini memang menggunakan mekanisme kuota 30 persen untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara di mana sebuah keputusan digodok, dilahirkan, dan harus dilaksanakan.
Berbagai kendala
Itu idealnya. Di tingkat praktis kita menghadapi berbagai kendala. Persoalan paling laten adalah karena ruang publik bukanlah ruang yang siap dan mengerti mengapa keterwakilan penting. Ini jelas karena sejak awal dunia politik dibangun di arena publik yang berangkat dari dikotomi yang memisahkan domain lelaki dan perempuan atau ruang publik dan privat/domestik. Inilah kritik fundamental para feminis terhadap konsep ruang publik gagasan Jurgen Habermas itu.
Konsep ruang ini tak menghitung kepentingan mereka yang selama ini ”dirumahkan” seperti perempuan dan kaum difabel. Akibatnya, ketika perempuan hendak masuk ke ruang itu, mereka dianggap penumpang gelap yang akan menggeser dan jadi pesaing atas dominasi lelaki yang merasa pemilik sah lembaga itu.
Di tingkat rumah tangga dan komunitas, perempuan berhadapan dengan efek biner yang sama. Pandangan budaya, agama, bahkan politik telah mendefinisikan status perempuan secara ajek sebagai ibu rumah tangga. Itu berarti, di ranahnya sendiri, mereka bukan pemegang kuasa dan otoritas. Mereka penumpang yang peran dan statusnya ditentukan pihak lain yang dianggap nakhoda (suami/keluarga besar). Ini berdampak besar ketika perempuan ”nyaleg”. Keputusannya sangat ditentukan sejauh mana suami memberi dukungan, termasuk pendanaan. Di sejumlah kasus, keterwakilan mereka perpanjangan tangan suaminya yang secara politik tak memungkinkan untuk maju sendiri.
Soal lain, langkah afirmatif hanya mensyaratkan ”angka”. Perempuan calon harus berhadapan dengan sikap yang meragukan kemampuan mereka. Sebuah sikap yang hampir tak pernah berlaku pada lelaki meski kualitas mereka luar biasa kedodoran. Masalahnya karena arena itu dianggap ruang main mereka, publik sering kali punya permakluman atas kedunguan mereka, sebuah sikap yang tak berlaku bagi perempuan. Lihat saja ketika Angel Lelga mempertontonkan ”kelasnya” di media televisi, ia sontak jadi bulan-bulanan. Olok-olok yang sama sebetulnya bisa dilontarkan kepada anggota DPR yang juga ”dodol”, tetapi bagi mereka seperti ada permakluman atas ketidakwarasannya.
Dari tiga persoalan ini saja dapat dibaca betapa tak gampang memastikan upaya arif yang bisa menjamin keterwakilan perempuan. Hampir pasti, upaya afirmatif di mana pun di dunia berangkat dari keadaan yang memang perempuan sendiri tak/belum siap masuk ke gelanggang politik. Ini disebabkan perlakuan diskriminatif yang telah lebih dulu menerpa mereka. Karenanya, upaya lanjutan yang dapat memastikan keterwakilan itu bisa terkawal terus diupayakan. Ini agar keterwakilan itu memiliki kepastian dan tak hanya di tingkat angka, tetapi juga makna.
Dalam konteks politik di Indonesia, kita menyaksikan bagaimana keterwakilan itu didemonstrasikan dalam pemilu legislatif. Upaya-upaya sistemik agar perempuan terwakili di setiap jenjang relatif telah dipatuhi partai. Praktis tiap partai di setiap dapil memasang perempuan. Dari sisi ini, afirmatif di tingkat paling elementer telah terpenuhi. Namun, soal keterpilihan, masalah lain. Afirmatif tak berlaku pada tingkat pemilihan. Lelaki dan perempuan dari satu partai sama harus bersaing mem-
perebutkan kursi. Ini berarti seorang caleg perempuan tak hanya harus bersaing dengan sesama calon dari partainya di dapil sama, tetapi juga dengan lelaki dan perempuan lain di satu dapil dari partai berbeda.
Gempa politik
Persaingan serupa ini pada kenyataannya memang jadi ”gempa politik” bagi caleg perempuan. Seperti Kak Zu, demikian saya memanggilnya. Ia semula hanya guru TK/PAUD yang dibangun partai lokal yang berkuasa di Aceh dengan gaji Rp 500.000. Ayahnya penarik becak, suaminya sopir. Februari 2013 saat partai panik menentukan daftar calon sementara, pamannya dari partai lokal—lawan partai berkuasa—membujuknya nyaleg dengan janji partai akan bantu. Ajakan bukan tanpa alasan. Ia menggenapi aturan keterwakilan 30 persen perempuan karena tanpa itu partai akan tercoret.
Kak Zu menyangka ia hanya akan main air semata kaki. Nyatanya, belanja politik untuk partai dan kampanye menenggelamkannya hingga ke leher. Ia sejak awal sadar, perannya hanya ”timun bengkok (untuk) memenuhi keranjang”. Begitu masuk, ia terseret ke pusaran arus kampanye yang nyaris kalap. Mobil suaminya dijual. Sepanjang kampanye, suaminya harus mengawal. Praktis mereka berdua tak lagi mencari nafkah enam bulan. Modal habis, ia meminta bantuan ayahnya yang kemudian menggadaikan kebun rambutannya.
Menangkah? Tidak. Kehidupan keluarga itu guncang. Suami tak bisa kembali ”narik” karena dianggap pengkhianat partai penguasa yang menguasai lintasan ”trayek”. Kak Zu harus cari sekolah baru karena posisi lama digantikan orang. Mereka sempat mengungsi ke rumah orangtua akibat ancaman kekerasan.
Kasus Kak Zu pasti bukan pengecualian dan tak bisa dijadikan alasan surut langkah. Yang harus dipikirkan, bagaimana melanjutkan kebijakan politik afirmatif tanpa menimbulkan gempa politik dan gelombang tsunami di keluarga. Dari pengalaman sejumlah negara seperti India, 10 tahun pertama upaya afirmatif tak gampang. Di tahun-tahun pertama keterwakilan perempuan diisi dinasti penguasa seperti juga di Indonesia. Namun, karena mereka masyarakat pembelajar, dalam waktu singkat keterwakilan itu membuahkan hasil bukan hanya bagi perempuan, melainkan juga bagi perbaikan negeri itu. Kebijakan-kebijakan terbaru yang dilahirkan membawa perubahan sangat signifikan terhadap cita-cita, apresiasi warga terhadap kaum perempuan. Antara lain dengan melawan politik uang dan korupsi di lembaga negara dan dengan cara itu memperlihatkan signifikansi keterwakilan perempuan di parlemen.
Lies Marcoes, Peneliti
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006096427
-
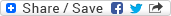
- Log in to post comments
- 498 reads