Sistem Tumpang Sari
Hutan untuk Ketahanan Pangan
Oleh: Ichwan Susanto
BIASANYA pelaku usaha hutan tanaman industri memanfaatkan alat berat untuk membongkar lahan agar bisa ditanami. Meski prosesnya cepat, cara ini membutuhkan biaya tinggi. Sejak 2007, PT Inhutani II (Persero), pemilik izin konsesi di berbagai kawasan belantara Kalimantan, menjajal cara konvensional, yaitu memanfaatkan tenaga manusia.
Pendayagunaan tenaga masyarakat setempat ini dinilai jauh lebih murah. Dampak sosialnya pun sangat positif karena menjadi strategi jitu mengatasi perambahan. Masyarakat yang membutuhkan lahan dan pangan tetap bisa menanam dan memetik hasilnya, kawasan hutan terjaga, serta biaya operasional perusahaan mampu dihemat.
Hal itu ditunjukkan Inhutani II saat rombongan wartawan yang diundang Kementerian Kehutanan melihat pengelolaan kawasan hutan produksi di Pulau Laut, Kotabaru, Kalimantan Selatan, pertengahan Februari 2014.
Selama 1,5 jam perjalanan dari ibu kota Kotabaru, melewati jalan perkerasan yang sebagian kondisinya berbentuk kolam lumpur, di kanan-kiri jalan tampak sawah ladang, kebun sawit, dan karet yang ditanam warga di area konsesi Inhutani II. Perambahan berlangsung sedikit demi sedikit layaknya penyakit kanker yang akhirnya meluas.
Hampir tak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan kegiatan itu. Keterbatasan pengawasan serta akses jalan yang sulit ditembus seolah memberikan kemudahan untuk menggerogoti hutan negara.
Ini yang menjadi salah satu tantangan bagi Inhutani II yang dipercaya mengelola areal seluas 48.720 hektar hutan tanaman industri di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Areal tersebut masih ditambah 40.950 hektar hutan alam dari total lebih dari 330.000 hektar hutan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Meski memiliki cakupan pengelolaan kawasan yang sangat luas, badan usaha milik negara ini kesulitan membiayai kegiatan operasional dan produksinya. Berturut-turut, sejak 2010, mereka mencatatkan kerugian usaha sebesar Rp 9,875 miliar (2010), Rp 36,822 miliar (2011), dan Rp 14.883 miliar (2012).
Harga kayu untuk bubur kertas, yang hanya ditentukan beberapa perusahaan pulp and paper raksasa, membuat nilai tawar penghasil kayu ini rendah. Tak mengherankan jika dengan usaha sendiri, mereka kesulitan melakukan penanaman kembali Acaccia mangium yang telah dipanen.
Ketidakmampuan melakukan penanaman lagi membuat sebagian areal tebang dalam kondisi terbuka. Ini belum termasuk areal yang telah dirambah menjadi sawah ladang, kebun sawit, dan karet.
Kalau kondisi ini tidak mendapatkan solusi, areal panen akan semakin menyempit dan daur pemanenan tak berkelanjutan. Sejak akasia ditanam sampai siap panen perlu 8 tahun.
Salah satu solusi yang ditemukan Inhutani II adalah memanfaatkan kayu akasia yang berdiameter besar sebagai bahan pertukangan yang bernilai jual lebih tinggi.
Cara lain, mencari modal untuk investasi diversifikasi hutan tanaman. Pinjaman ini didapatkan dari Koperasi Korea-Indonesia (PT Korea Indonesia Forestry Cooperative/KIFC) dengan mekanisme pinjaman lunak dan bagi hasil penanaman karet dan akasia mulai 2010.
Konvensional
Untuk menghemat pendanaan, sejak 2007, Inhutani II mengerahkan tenaga konvensional, yaitu manusia, dalam pembersihan/penyiapan areal tanam. Meskipun proses penyiapan areal tanam menjadi lebih lama, tetapi efisiensi biaya bisa tercapai.
Dengan mengandalkan petani untuk membersihkan areal tanam, biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan pembersihan areal dengan alat berat yang mencapai sekitar Rp 4 juta per hektar.
Setiap keluarga yang terlibat diberi kompensasi Rp 1,25 juta per hektar serta berbagai bantuan pupuk dan pestisida. Petani dipersilakan menanam padi gogo di sela-sela bibit tanaman Acaccia mangium yang berjarak tanam sekitar 3 meter x 3 meter persegi. Saat panen, tanaman tumpang sari itu 100 persen hasilnya untuk petani.
Saat ini ada sekitar 650 hektar areal tumpang sari yang diusahakan petani setempat. Setiap tahun, rata-rata 2.000 hektar tanaman akasia dipanen dan membutuhkan penanaman kembali. ”Semakin luas yang bisa dimanfaatkan petani tumpang sari, kami sangat senang,” kata Tjipta Purwita, Direktur Utama PT Inhutani II.
Sistem yang saling menguntungkan ini dinilai menjadi hal positif dalam pengelolaan hutan tanaman lestari. Artinya, setiap tahun selalu tersedia tegakan siap tebang yang sekaligus merupakan lahan siap tanam. Lahan siap tanam ini merupakan areal yang potensial bagi tanaman pangan.
Sangat bermanfaat
Bagi petani, hasil panen padi sangat signifikan. Rata-rata, tiap hektar mampu menghasilkan 2 ton–6 ton gabah kering giling. ”Tahun kemarin cuma dapat 2 ton gabah karena serangan tikus,” kata Dili (60), petani asal Desa Tanjung Seloka, yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dari area penanaman.
Selain hama tikus, sawah yang berimpitan langsung dengan hutan sering diganggu babi dan burung. Karena itu, selama masa perawatan dan menjelang panen, Dili yang menjadi satu dari 300 keluarga anggota Kelompok Tani Rindu Bertani ini tinggal di gubuk-gubuk sementara di sekitar ladang. Mereka bisa dua pekan berpisah dari keluarga di desa.
Meski demikian, para petani senang karena hasil yang didapat memadai untuk konsumsi sendiri ataupun dijual. Hanya, sistem tumpang sari memiliki kekurangan, petani harus mengikuti daur panen perusahaan.
Artinya, tumpang sari hanya bisa dilakukan dalam satu periode tanam. Penyebabnya, dalam waktu setahun, tanaman pokok yaitu akasia telah tumbuh tinggi dan menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan tanaman padi. ”Kami harus menyediakan sarana transportasi dari desa ke areal tumpang sari. Saya rasa, biayanya masih masuk,” kata I Gede Putu Mariasa, GM Jasa Kehutanan dan Usaha Lain Inhutani II.
Sistem tumpang sari selain murah juga signifikan meningkatkan kualitas kayu akasia. Mariasa menunjukkan beberapa demplot alias petak percontohan akasia berusia sama yang dikerjakan dengan sistem mekanis dan tumpang sari.
Hasilnya, tanaman akasia yang ditanam dengan cara tumpang sari tampak lebih hijau dan segar daripada yang ditanam dengan sistem mekanis. Batangnya pun lebih tinggi dan berdiameter lebih lebar. Kemungkinan penyebabnya, akasia di lahan tumpang sari mendapatkan manfaat dari pemupukan petani pada tanaman padi.
Melihat kerja sama yang saling menguntungkan ini, sepertinya hutan yang sangat luas bisa dilirik mengatasi masalah keterbatasan areal pertanian.
Secara umum, sejak 1998 hingga 2010, sektor kehutanan memasok pangan dari areal tumpang sari seluas 6,3 juta hektar per tahun. Tak hanya di Inhutani II, pola tumpang sari di sela-sela pohon yang diterapkan di banyak pemegang izin konsesi ini juga mampu menghasilkan 9,4 juta ton komoditas pangan per tahun, mulai dari padi, jagung, sampai kedelai.
Angka ini masih sangat jauh dari potensi yang ada. Masih ada jutaan hektar areal tanam yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bertanam tumpang sari. Petani dan pemilik konsesi bisa diuntungkan, kedaulatan pangan pun tercapai.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000004886728
-
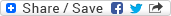
- Log in to post comments
- 336 reads