Terpinggirkan di Tanah Sendiri
KEBIJAKAN otonomi khusus seolah menjadi mantra ajaib untuk Papua. Triliunan rupiah digelontorkan dengan keyakinan bisa membuat provinsi tersebut menjadi lebih maju. Namun, hal itu dilakukan tanpa pengawasan yang ketat.
Sumber daya alam berupa mineral, kekayaan hutan, dan laut Papua sebenarnya tak akan habis digunakan untuk memberi makan penduduknya yang hanya 2.851.999 jiwa. Penambangan emas di Mimika, misalnya, pada 2010 memberi PT Freeport keuntungan hingga Rp 4.000 triliun. Freeport juga menjadi penyetor pajak terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 1 miliar dollar AS per tahun (Sri Yanuarti, LIPI, 2012).
Kebijakan otonomi khusus (otsus) yang diterapkan di Papua sejak tahun 2002 memungkinkan wilayah ini menerima kucuran dana berlimpah. Sejak 2002 hingga 2013, dana otsus yang telah dikucurkan pemerintah pusat ke Papua Rp 32,709 triliun (Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua). Pada 2014, jumlah itu bertambah Rp 4,777 triliun dan Rp 2,5 triliun yang berasal dari dana infrastruktur.
Namun, semua kelimpahan itu belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan di Papua. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, proporsi penduduk miskin Papua pada September 2013 masih 31,53 persen, jauh di atas angka nasional (11,37 persen). Indeks Pembangunan Manusia Papua juga ada di peringkat terendah nasional. Indikator itu jadi sinyal penting atas situasi nyata kehidupan masyarakat Papua.
Jika kita berjalan-jalan di pasar lokal, seperti Pasar Misi di Wamena, tampak jelas segregasi antara pedagang asli Papua dan non-Papua. Pedagang asli Papua menggelar dagangannya di tanah, sementara yang non-Papua menempati kios-kios pasar.
Jenis dagangan yang digelar para mama Papua hanya 5-10 ikat keladi, pinang, atau sayuran lainnya. Sementara kios-kios pasar dipenuhi barang-barang kebutuhan pokok. Sektor transportasi ataupun perdagangan umumnya dikuasai para pendatang.
”Program otsus tidak berhasil mendorong masyarakat asli mengambil peran-peran ekonomi,” kata Thaha Al Hamid, Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua. Kenyataan ini mengingkari salah satu tujuan otsus, yaitu memberdayakan ekonomi warga Papua.
Kegagalan itu berpotensi menciptakan migrant capture di Papua. Akses terhadap proses dan manfaat pembangunan pun ditangkap dan dikuasai para migran non-Papua. Orang Papua mengalami peminggiran, tak ikut menikmati pembangunan. Kalaupun ada, hanya segelintir elite Papua, terutama mereka yang punya jabatan birokrasi (John Jonga dan Cypri JP Dale, 2011).
Proses peminggiran sudah tampak dari perubahan komposisi penduduk. Penelitian Jonga dan Dale menyebutkan, akibat dari transmigrasi resmi pada masa Orde Baru ataupun migrasi spontan, komposisi penduduk Papua dan non-Papua berubah dari 96 : 4 menjadi 49 : 51 pada 2010.
Pertumbuhan penduduk asli Papua hanya 1,84 persen per tahun, sementara non-Papua 10,82 persen. Dengan demikian, dalam tiga dekade ke depan warga Papua akan menjadi minoritas di tanah mereka sendiri.
Kekerasan
Marjinalisasi orang asli Papua diwarnai pula oleh berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Kebijakan otsus tak menghentikan kekerasan. Di samping kekerasan politik, seperti pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Opinus Tabuni, Mako Tabuni, peristiwa Abepura 2011 dan Wamena 2012, tak sedikit kekerasan yang terjadi karena dipicu pilkada ataupun konflik dengan perusahaan tambang dan pemegang hak pengusahaan hutan.
Pengambilalihan tanah ulayat oleh perusahaan besar kerap menyisakan masalah. Bukan saja kompensasi yang tak sebanding, melainkan juga ”perampasan” tanah, alat produksi, dan sumber penghidupan mereka yang diikuti dengan penghancuran ekologi. Sebagian warga yang kehilangan tanah ulayatnya beralih menjadi pekerja di proyek.
Jika proses peminggiran terus terjadi, bahkan diwarnai kekerasan, otsus yang bercita-cita memajukan Papua bukan tak mungkin justru membangkitkan kembali ingatan akan kemerdekaan.
(BI Purwantari/Litbang Kompas)
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005293524
-
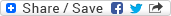
- Log in to post comments
- 184 reads