Tenun Tanimbar dalam Evolusi
Oleh: Mohammad Hilmi Faiq 0 Komentar FacebookTwitter
Untunglah petenun Tanimbar masih menggunakan alat tradisional sehingga mereka tak bergantung pada listrik yang dalam sehari bisa lima kali padam.
Yeshinta Klise alias Yanti (37) menenteng panci berisi air ke dapur yang berada di bawah pohon mangga di samping rumahnya di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku. Dia tak jadi menjerang air di dalam rumah karena listrik padam sehingga kipas angin tak berfungsi. Pohon mangga menyelamatkannya dari hawa panas dan terik mentari.
Yanti lantas menata batu sebagai tungku dan mengambil kayu untuk membuat api. Setelah air mendidih, dia menuangkan pewarna kimia yang dibeli dari toko. Beberapa menit kemudian, dia mencelupkan benang putih yang sebagian telah diikat. Tak lebih dari 10 menit, benang itu berubah menjadi hitam. ”Bagian diikat ini yang nanti tetap putih dan menjadi motif tenun,” katanya.
Tenun Tanimbar disebut tenun ikat lantaran ada bagian benang yang diikat atau ditutupi dengan rafia (dulu petenun menggunakan daun lontar) untuk melindungi bagian tertentu agar tidak turut berubah warna. Teknik ini sudah ratusan tahun dilakukan sebelum merebak pewarnaan kimia.
Proses pewarnaan menggunakan bahan kimia sudah sangat jamak di Kepulauan Tanimbar setelah sepenuhnya meninggalkan pewarnaan alam karena rumit dan sulit. Pewarnaan menggunakan bahan kimia selesai dalam hitungan menit, sementara dengan bahan alam butuh beberapa hari. ”Bahannya pun sekarang sulit dicari,” kata Nanda Luturmase (77), petenun di Olilit Barat.
Nanda menceritakan, hingga tahun 1980-an, masih banyak petenun menggunakan pewarna alam. Warna hitam diperoleh dari jelaga lampu minyak atau dedaunan, sementara warna coklat dan merah dari batang tanaman bakau. Petenun biasanya meminta bantuan suaminya untuk mencari bahan pewarna alam itu di hutan.
Keterangan ini sebangun dengan penjelasan P Drabbe, misionaris Belanda yang pernah tinggal selama 20 tahun di Tanimbar dan menulis buku Leven van den Tanembarees (Leiden, 1940). Buku ini menceritakan proses pemetikan kapas, pemisahan biji, pemintalan, hingga pewarnaan benang. Untuk mewarnai, benang direndam di dalam air bercampur daun selama sehari semalam. Setelah itu, benang direndam lagi ke dalam air kapur selama dua hari agar warnanya tahan lama.
”Seng (tidak) ada lagi. Tinggal kain kapas yang ada,” kata Fone Lerebulan (28), warga Desa Kandar, Pulau Selaru. Dia lantas menunjukkan selembar kain berbahan benang kapas yang dia warisi dari orangtuanya.
Petenun juga meninggalkan kapas sebagai bahan baku karena alasan yang sama: ribet. Mereka kini beralih ke benang sintetis berbahan katun dan nilon meski kapas sangat berjasa sebagai bahan baku tenun sebelum mereka mengenal benang sintetis. Kini tinggal 1-2 petenun yang sesekali menenun dengan benang kapas.
Tenun ikat Tanimbar telah berevolusi. Bukan hanya pada sisi bahan dan pewarnaan, melainkan juga pada motif dan kegunaan. Drabbe mencatat setidaknya ada 16 motif dan nama kain yang dikenal luas masyarakat Tanimbar pada masa penjajahan Belanda saat dirinya menyebarkan agama Katolik di sana. Nama itu antara lain tais matan, tais maran (bergaris hitam putih di kedua sisi kain), tais fuit (berbentuk sarung tanpa motif), dan tais lar’tameru (layar tameru, mengacu pada nama marga). Adapun motif yang terkenal antara lain ule rati, tunis (tombak), suar (janur), dan lelemuku (anggrek). Warna dasar kain pun cenderung gelap seperti hitam dan coklat tua. Adapun dalam buku Tenun Tradisional Tanimbar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, W Pattinama menyebut terdapat 41 ragam hias.
Motif-motif itu muncul sebagai hasil interaksi manusia dengan alamnya. Suku Tanimbar yang kerap berperang dan berburu mengabadikan tombak dalam tenunnya sebagai simbol keperkasaan. Motif ule rati konon terinspirasi dari serangan hama ulat pada tanaman warga. Di balik serangan hama yang merusak itu, mereka melihat keindahan yang kemudian abadi dalam tenun ikat.
Cenderung terang
Belakangan, warna kain kian variatif dan cenderung terang, seperti warna merah muda, hijau muda, dan biru menyala. Sebagian kain malah diselipi benang emas sehingga terkesan menyala dan berkilau. Motifnya pun nyaris tak dikenali lagi karena benar-benar baru atau pengembangan dari motif lama. Ada motif yang mirip tombak (tunis), tetapi sudah dimodifikasi.
Kain tenun jenis itu banyak sekali ditemui di Pulau Selaru, seperti di Desa Lingat dan Kandar. Gaya ini mulai menyebar ke Pulau Yamdena, pulau terbesar di Kepulauan Tanimbar, meski masih banyak yang menenun dengan warna dasar hitam. ”Tenun di Selaru banyak dipengaruhi budaya Ambon karena misionaris di sana berasal dari Ambon. Warnanya cerah dan motifnya berbeda dengan motif klasik Tanimbar,” kata Ety I Werembinan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Yang menggembirakan, tenun ikat tidak melulu untuk acara adat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggairahkan modifikasi kain tenun untuk rompi sekolah dan pakaian para pegawai negeri sipil. Ini untuk mengerek pamor tenun ikat Tanimbar. Miss Kanada Camille Munro sempat membalut tubuhnya dengan tenun ikat Tanimbar di ajang Opening Show Miss World 2013 di Bali. Ini berdampak promotif bagi tenun ikat.
Para petenun sempat merasakan madu kegairahan modifikasi. ”Sebulan bisa nabung sampai Rp 3 juta karena banyak yang pesan untuk rompi. Sekarang sepi lagi. Paling dapat Rp 1 juta kalau ramai pesanan,” kata Yanti yang masih mengandalkan penghasilan suaminya sebagai kuli bangunan. Sejak 2012, kampanye pemakaian kain tenun modifikasi untuk seragam sekolah dan PNS mengendur.
Ety Werembinan mencoba menggairahkan kembali modifikasi kain tenun untuk fungsi lain, seperti tas, sepatu, bahkan penghias gelas dan botol. Beberapa prototipe dia pajang di lemari kantornya. Sebagian besar modifikasi itu dikerjakan di Jakarta karena teknologi lokal belum memadai.
Sementara itu, pola pemasaran masih sangat konvensional. Para petenun di Pulau Selaru mengumpulkan hasil karyanya di Toko Ebsiha di Saumlaki, yang menjadi penampung sejak puluhan tahun lalu. Petenun lain mengandalkan pesanan. Ada juga yang mengirimkan kepada saudaranya di Jakarta untuk dijual.
Petenun maestro
Nanda Luturmase risau dengan perkembangan tenun ikat Tanimbar. Dia senang kain tenun berkembang, tetapi sedih karena banyak anak muda yang meninggalkan tradisi menenun. Yang bertahan menenun pun mulai melupakan motif-motif klasik. ”Anak saya dulu menenun. Namun, karena hasilnya tidak cukup untuk makan, dia sekarang jualan sayur di pasar,” kata Nanda yang menguasai belasan motif klasik tenun ikat Tanimbar ini.
Dulu, semua gadis Tanimbar menenun. Sebab, jika tidak menenun, mereka tidak mempunyai pakaian. Kini, mereka menilai, menenun tidak menjanjikan. Rata-rata dari 10 gadis Tanimbar tinggal dua atau tiga yang mengenal tenun. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Maluku Tenggara Barat, tinggal 200-an petenun yang masih sangat aktif.
Para pemudi Tanimbar cenderung memilih pekerjaan lain seperti jadi pedagang dan pegawai. Erna Kelbulan (25), warga Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Saumlaki, mengaku tak bisa menenun. Dia memilih kuliah di Jawa dan kelak mencari pekerjaan sebagai orang kantoran. Sikap Erna ini banyak dianut para gadis Tanimbar.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010509827
-
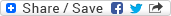
- Log in to post comments
- 924 reads