Daya
Juwita dan Tenun Jelita
Dari tangannya lahir berlembar-lembar tenun indah berkualitas tinggi yang menjadi koleksi para kolektor kain Indonesia. Keluarga Juwita Jafar (41) menjadi satu-satunya keluarga penenun di dusunnya di pelosok Ende, Nusa Tenggara Timur.
Penampilannya sangat sederhana. Wajahnya juga penuh senyum. Setiap kali ia membawa kain-kainnya ke Jakarta, para pelanggannya akan berdatangan. Juwita umumnya mengenal semua pelanggannya karena mereka selalu kembali datang menemuinya.
Alhasil, ia kerap ”tidak tega” kalau pembelinya sudah menawar harga kain. Apalagi, kalau diembeli kata-kata, ”Kan, saya sudah langganan.” Sering, Juwita menyerah dengan harga yang di bawah standar. ”Saya suka tidak enak kalau menolak soalnya mereka sudah jadi langganan,” kata Juwita.
Padahal, di kampungnya sendiri, di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Moni Kelimutu, Kabupaten Ende, hasil karyanya dihargai pantas. ”Biasanya kalau untuk acara khusus, seperti pernikahan, mereka membeli tenun dari saya. Mereka membeli bisa sampai Rp 3 jutaan. Untuk harga segitu pun tenaga saya tidak dihitung,” katanya.
Lihatlah kemolekan tenun Juwita yang seperti juga umumnya tenun Nusa Tenggara Timur merupakan tenun ikat lungsi dengan warna-warna yang cenderung gelap, seperti hitam, coklat, biru, merah marun, merah keunguan, kuning kunyit, dan putih. ”Saya mencari kapas di hutan, lalu saya pintal jadi benang,” lanjut Juwita yang sesekali tetap membuat tenunan dari benang sintetis untuk konsumen di pasar lokal.
Ada begitu banyak tahapan yang dilakukan sebelum dimulai penenunan, seperti memisahkan kapas dari biji, kemudian memintalnya menjadi benang. Benang-benang itu kemudian digulung dan diwarnai dengan menggunakan bahan pewarna alam. ”Bahan-bahan itu saya cari di hutan dan ada juga di sekitar rumah,” lanjut Juwita.
Untuk warna hitam, misalnya, Juwita menggunakan abu dapur dari kelapa. Untuk warna oranye bisa diambil dari akar mengkudu, sedangkan untuk warna kuning dari akar kunyit. ”Akarnya ditumbuk, dimasak, lalu ditambah kemiri tumbuk agar sarung tidak kelihatan kusam,” tambah dia.
Setelah pewarnaan selesai, barulah ia mengikat motif dengan menggunakan pucuk daun kelapa. Ini merupakan proses yang rumit karena membutuhkan ketelatenan dalam menghitung lajur benang. Jika proses mengikat motif selesai, penenunan pun dimulai.
Banyak pengaruh
Meskipun sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur adalah Nasrani, Ende merupakan salah satu dari sedikit wilayah yang dipengaruhi Islam. Letaknya yang berada di pesisir juga memungkinkan wilayah ini bersentuhan dengan kaum pendatang, khususnya Eropa pada masa kolonial.
Hal itu berpengaruh pada motif-motif tenun yang dihasilkan di sini. Pengaruh Islam membuat motif-motif yang muncul pada lembaran kain tidak menampilkan secara utuh sosok binatang ataupun manusia, tetapi disimbolkan dalam siluet yang geometris dan repetitif.
Dalam karya-karya Juwita, misalnya, cicak dan kupu-kupu muncul bak garis-garis yang berulang. Hampir semua motif diambil dari benda ataupun pemandangan yang ada di sekitar, seperti masjid, bunga, tombak, gunung, biji kacang, dan perhiasan anting. Pengaruh Eropa terlihat di sejumlah motif, seperti motif bunga mawar, sementara pengaruh India terlihat pada motif patola yang khas.
”Sejak kecil, saya hanya menghafalkan apa yang diajarkan nenek saya. Ini motif cicak, ini motif masjid, ini kacang,” kata Juwita yang belajar menenun sejak usia belia.
Kain tenun umumnya digunakan untuk sarung atau lawo (kadang dilafalkan zawo), juga untuk selendang dan selimut anak. Begitu banyak jenis sarung yang masing-masing memiliki fungsinya. Ada Lawo Ndea, Lawo Pundi, Lawo Mogha, Lawo Kalimua, Lawo Daki’ Ngghera, dan lainnya. Lawo Pundi, misalnya, digunakan untuk pesta adat atau menari karena kain ini melambangkan keagungan. Sementara jenis sarung Lawo Luka, menurut Juwita, memiliki tingkat pembuatan yang tersulit dan biasanya digunakan untuk acara khusus.
”Lawo Luka dengan motif kaki masjid, misalnya, adalah sarung yang paling nomor satu. Warnanya juga nomor satu dan pembuatannya paling susah karena punya hitungan benang yang rumit, harus presisi. Kalau tidak sama, pikiran kita sedang tidak betul. Untuk Lawo Luka saya bisa membuat sampai setahun,” kata Juwita.
Juwita merupakan generasi keempat di keluarganya yang menjadi penenun. Ia masih menyimpan sejumlah tenunan karya buyutnya yang sudah berusia ratusan tahun dan dijadikan prototipe untuk motif-motif kuno yang saat ini sudah punah. ”Kami memang tidak biasa mencatat, semua motif itu saya hafalkan,” kata Juwita.
Kini, bersama dengan saudara-saudara kandungnya yang tinggal seatap, keluarga ini meneruskan tradisi menenun yang sudah dirintis para leluhurnya. ”Dulu banyak keluarga yang menenun di desa ini, sekarang tinggal keluarga kami saja,” ucap Juwita.
Prihatin
Jangan bayangkan kehidupan Juwita seindah tenunnya. Juwita hanya berpendidikan sampai kelas 2 SMP karena orangtuanya tidak mampu menyekolahkannya. Lewat menenunlah ia membantu kedua orangtuanya sampai ia menikah. Pada 1997, ketika bayinya berusia sembilan bulan, sang suami meninggal. Ia kembali membangun kehidupan dari titik nol dengan penuh keprihatinan.
Untuk makan sehari-hari sampai kini pun Juwita kadang tidak menyentuh lauk-pauk. ”Kami hanya makan seadanya, kadang hanya dengan garam, kadang cukup dengan sambal, kan, cabainya tinggal ambil di depan rumah. Tidak apa, saya sudah biasa,” ujarnya.
Merujuk pengalaman dirinya yang pernah putus sekolah, Juwita berupaya keras memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak semata wayangnya. ”Saya selalu berdoa anak saya bisa sekolah setinggi-tingginya. Alhamdulillah saya dikaruniai anak pintar, sejak SD sampai SMA dia selalu juara,” kata Juwita, matanya berbinar menceritakan putranya, Imran Mursalim, yang kini melanjutkan kuliah kepariwisataan di Yogyakarta. ”Semoga nantinya dia bisa ikut membantu mengembangkan pariwisata di Kelimutu. Daerah kami indah sekali,” kata Juwita
Juwita menyimpan cita-cita lain. Melalui karya tenunnya, ia ingin memperbaiki rumahnya yang sudah nyaris ambruk. Sulit dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkannya agar uang terkumpul.
”Kami berenam setahun maksimal bisa menghasilkan hanya 20 sampai 30 kain. Jadi, saya terpaksa menjual sebagian tenun warisan untuk bisa membeli bahan-bahan bangunan,” kata Juwita. (MYRNA RATNA)
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010653198
-
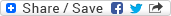
- Log in to post comments
- 470 reads