Bergumul dan Berharap Kepada Papua
Pastor Yohanes Djonga Pr
Oleh: Aryo Wisanggeni & Budi Suwarna 0 Komentar FacebookTwitter
Selama 27 tahun, Pastor Yohanes Djonga Pr bergumul dan menyelami berbagai persoalan pelik orang Papua. Dari seorang guru, ia menjadi seorang aktivis hak asasi manusia.
Dingin malam yang menyengat menyeruak ketika Pastor Yohanes Djonga Pr membuka pintu dan memasuki pastoran Paroki Hepuba, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Desember 2013. Ia baru bersepeda motor menembus hujan, pulang dari kelas pendidikan advokasi hak asasi manusia untuk anak muda di Wamena, ibu kota Jayawijaya.
Seorang pemuda memojok di sudut dapurnya yang gelap. Percakapan lirih keduanya menebar ketegangan, terasakan ada sesuatu yang salah, entah apa dan di mana. Mereka bercakap lirih. ”Baik, kalau begitu saya segera pergi ke kampung mereka,” ujarnya menyudahi percakapan.
”Saya harus pergi,” ujar Pater John, panggilan bagi Pastor Yohanes Djonga Pr, kepada kami. Dengan ringkas ia mengisahkan sebuah pertikaian di antara dua kampung bertetangga yang terjadi pada 2012. Proses perdamaian di antara kedua kampung belum tuntas karena denda babi belum selesai dibayar, dan tiba-tiba kedua kampung bersiap untuk bertikai lagi.
”Tadi pagi sepeda motor yang dikendarai pemuda salah satu kampung menyerempet warga kampung sebelahnya. Sekarang kampung sebelah bersiap menyerbu kampung si pengendara motor itu. Kalau proses perdamaian hancur oleh pertikaian baru, urusannya bisa panjang. Saya harus pergi ke kampung mereka sekarang juga,” katanya.
Posisi pelayanan
Masalah yang terjadi di Papua, khususnya di Jayawijaya, sulit dibayangkan oleh orang yang jauh dari Papua. Di sini apa saja bisa menjadi masalah serius hingga pertikaian atau pembunuhan. ”Namun jika kita mau mengajak bicara pasti ada jalan keluar untuk menghindarkan pertumpahan darah,” katanya.
Anda menjadi pemimpin umat, aktivis hak asasi manusia (HAM), juga mengajar. Bagaimana Anda melihat posisi pelayanan?
Ini saya tidak tahu (tertawa). Ketika saya belum menjadi pastor, saya terlibat sejumlah advokasi HAM, dan bersama sejumlah aktivis HAM di Papua mendirikan Kontras Papua (sebuah lembaga swadaya masyarakat advokasi HAM di Jayapura). Apakah saya seorang aktivis HAM atau seorang imam Katolik? Bagi saya kedua-duanya penting dan sama saja. Seorang imam harus menerapkan segala upaya untuk membela orang yang sedang berkesusahan. Menjadi imam itu bukan sekadar untuk ibadah saja, sakramen saja, bukan saja mengurus kebaktian. Yang lebih penting justru mengurus masalah sosial, masalah orang yang tidak memiliki akses untuk memperoleh bantuan.
Anda selalu bisa menjalaninya?
Tentu saya mengalami kesulitan untuk memverifikasi laporan dan pengaduan tentang berbagai persoalan di kampung, di distrik, di Paroki. Lembah Baliem sangat luas. Di berbagai wilayah, terjadi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan oleh aparat, perkelahian karena alkohol, pembunuhan, kasus kematian karena sakit, sekolah tanpa guru, puskesmas tanpa dokter. Saya ingin tiap laporan itu bisa diverifikasi dan diadvokasi, tetapi mengharapkan saya sendirian pasti tidak bisa. Itulah mengapa saya melatih para anak muda mengadvokasi berbagai masalah sosial.
Kelas pertama kami terdiri dari 26 orang muda dari Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Jayawijaya. Kami belajar membuat laporan investigasi, membuat film dokumenter. Kami sudah menggelar lima kali pelatihan, tapi baru menghasilkan dua film dokumenter advokasi berdurasi 10 menit. Ini memang tidak mudah.
Lebih buruk
Yohanes Djonga Pr baru dua tahunan bertugas di Paroki Kristus Penebus Telnyapike Hepuba, Distrik Asolokobal (distrik setingkat dengan kecamatan). Namun, Pater John adalah orang lama di Jayawijaya. ”Saya pertama kali datang ke Papua bertugas sebagai guru agama Katolik di Kimbim, Jayawijaya. Saya tiba di Wamena tanggal 12 Juli 1986,” ujarnya.
Imam kelahiran 4 November 1958 itu meninggalkan Jayawijaya 1990. Pada 2010, Pater John kembali mendapati beragam situasi sosial yang lebih pelik ketimbang situasi Jayawijaya ketika ia tinggalkan 20 tahun sebelumnya.
”Pelayanan publik di Jayawijaya pada 27 tahun silam justru lebih baik ketimbang kualitas pelayanan publik saat ini. Waktu itu, pelayanan kesehatan berjalan bagus, ada kepala desa yang menyelenggarakan program yang baik. Terlebih juga, pendidikan. Sekolah zaman dahulu tertib, bagus. Sebenarnya ini kecenderungan umum di Papua. Sejak Undang-Undang Otonomi Khusus diundangkan pada 2001, Papua justru semakin mengalami kehancuran.”
Mengapa pelayanan publik memburuk?
Sistem pemilihan kepala daerah yang memengaruhinya. Pemerintahan dibentuk dengan logika balas budi dan balas dendam. Secara umum kita melihat orang yang tidak memiliki keahlian, belum memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk sebuah jabatan, menjabat karena menerima balas budi setelah memberi dukungan dalam pemilihan umum kepala daerah.
Gelombang pemekaran di Papua tidak memperbaiki pelayanan publik?
Yang sekarang terjadi bukan lagi gelombang pemekaran, tapi tsunami pemekaran yang menghancurkan. Bagaimana mungkin satu desa berpenduduk 26 keluarga seperti Asso Lokobal dimekarkan. Hasil pemekarannya, ada desa yang terdiri 29 jiwa. Ketika desa dimekarkan, komunitas klan, suku, menjadi pecah. Kekuatan sosial berdasarkan suku dan klan tercerai-berai akibat pemekaran desa.
Pemekaran pemerintahan daerah hanya menjadi politik untuk mendapat anggaran lebih banyak, menghitung jumlah desa dengan manipulatif, menghitung jumlah penduduk secara manipulatif. Dalam pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur, Komisi Pemilihan Umum Daerah membuka dua tempat pemungutan suara dan mengirim 900 lebih surat suara ke Asolokobal. Padahal yang memilih hanya sekitar 140 jiwa saja.
Berarti kualitas pelayanan publik tetap sama?
Tidak, justru lebih buruk karena orang yang diangkat menjadi pejabat publik di daerah pemekaran sering kali tidak cakap. Seorang guru bisa menjadi seorang kepala distrik, setingkat camat. Padahal ada sekolah khusus untuk menjadi camat. Ada banyak kepala sekolah yang diangkat menjadi kepala dinas. Banyak sekolah tidak punya guru karena gurunya menjadi kepala dinas. Pemekaran justru melemahkan kapasitas pemerintah daerah.
Contoh, di Samnage, Kabupaten Yahukimo, yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya. Antara 1 Januari–30 Maret 2013, ada 62 orang meninggal karena sakit. Kader kesehatan mencatat bahwa mereka yang meninggal sempat mengalami flu, batuk, mengeluh sakit kepala, sesak napas, dan diare. Penyakitnya apa tidak diketahui, karena kader kesehatan itu SMP pun tak tamat. Tidak ada dokter.
Otonomi khusus tidak memperbaiki situasi?
Tidak, karena kebijakan pemerintah pusat pun tetap berkacamata Jakarta. Itu tampak dalam hancurnya ketahanan pangan orang asli Papua karena beras setiap bulan didrop dan dibagikan begitu saja. Masyarakat Lembah Baliem yang petani ulung dan ulet tidak mau lagi berkebun gara-gara terlalu sering menerima bantuan beras miskin dan bantuan uang tunai. Budaya konsumsi juga disuburkan terlalu banyaknya bantuan uang tunai. Uang bantuan perdesaan, uang rencana strategis pembangunan kampung. Di kampung tidak ada sistem administrasi atau manajemen yang baik. Contoh kasus di Distrik Bolakme, kepala desa setelah mendapat uang respek, hilang pergi ke Kota Wamena untuk menghabiskan uang.
Itu kesalahan penerima uang?
Yang salah adalah orang yang memberikan uang. Di Papua, orang bingung mengelola uang Rp 100.000. Apalagi diberi uang Rp 200-300 juta. Kita yang mengetahui bagaimana mengelola keuangan secara bodoh-bodoh masih menyerahkan uang itu. Memang ada para pendamping yang disertakan untuk membuat perencanaan program. Kenyataannya, yang terjadi ketika pendamping datang uang sudah habis.
Apakah tidak lebih baik pendidikan dan kesehatan diurus pemerintah pusat?
Kalau pemerintah pusat mau sungguh-sungguh membantu orang asli Papua, dan ingin melihat tanda kemajuan pelayanan publik, pemerintah pusat harus serius menangani pendidikan dan kesehatan di Papua. Jika tidak, saya tidak tahu seberapa lama Indonesia bertahan mengambil hati orang asli Papua. Setelah 12 tahun Otonomi Khusus, dengan uang triliunan rupiah ke Papua, masyarakat asli Papua tidak merasa mendapatkan manfaatnya.
Apa akar masalah Papua?
Orang Papua mempersoalkan manipulasi suara orang Papua dalam Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Itu persoalan politik, yang akhirnya menjadi meruncing dan meluas karena sakit hati masyarakat melihat buruknya pelayanan publik di Papua. Kini, soal politik itu bukan lagi satu-satunya soal.
Apa persoalan besar yang lain?
Persoalan yang kini menjadi masalah sangat besar adalah kehancuran sumber daya alam orang asli Papua. Kehancuran sumber daya alam menjadi persoalan hidup dan matinya orang asli Papua. Beras dan gula itu tidak penting. Namun kehidupan mereka (masyarakat subsistem yang berburu dan meramu hasil hutan) dengan lingkungannya, dengan binatang-binatang di hutan, dengan pohon-pohon di hutan, karena itu semua berkaitan dengan hajat hidup, nilai hidup, dan kebudayaan mereka. Hutan mereka dihabiskan untuk kebun kelapa sawit, perumahan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Orang Papua merasa, ’mereka mencuri tanah kami dan merusaknya’. Itu akar konflik vertikal lainnya.
Orang di Papua sering menyebut dialog, bukankah sudah ada dialog?
Sudah ada banyak dialog, tetapi tidak pernah membahas isu yang justru ingin dibahas oleh orang Papua. Dialog yang sudah terjadi tentang Otonomi Khusus, dialog tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Yang tidak pernah didialogkan justru persoalan politik, persoalan pelanggaran HAM, itu tidak pernah dibahas.
Mana kini yang lebih mendesak, persoalan kewenangan pendidikan dan kesehatan atau dialog?
Dialog, dan melalui dialog itu Jakarta dan Papua bisa bersepakat apa yang akan kita lakukan demi memperbaiki situasi Papua. Termasuk menyepakati pengambilalihan wewenang menyelenggarakan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Sekali lagi, cobalah memahami bahwa seluruh persoalan politik Papua meruncing karena buruknya pelayanan publik di Papua.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000004497098
-
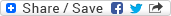
- Log in to post comments
- 158 reads