Catatan HUT ke-15 LAPAR: Demokrasi dan Pluralisme Kuat di Wacana
Rabu, 16 April 2014 23:43 WITA
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Tahun 1999 merupakan tahun awal kran demokrasi terbuka lebar. Pertumbuhan organisasi masyarakat sipil pun signifikan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi non pemerintah (Ornop).
Kehadiran organisasi masyarakat sipil seperti itu, di samping sebagai ekspresi terbebas dari kungkungan represif Orba sepanjang tiga dasawarsa lebih, juga sebagai tanda kuatnya keinginan masyarakat sipil berkonstribusi diatas panggung demokrasi.
Di tengah konteks itulah, atau tepatnya Tanggal 17 April 1999, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel, hadir sebagai salah satu LSM di Sulsel untuk memberi konstribusi terhadap dinamika demokrasi, khsusunya diaras lokal Sulsel.
Kehadiran LAPAR Sulsel berupaya sekuat mungkin terhadap pembangunan demokrasi yang kuat pula, dan pengelolaan pluralisme yang manusiawi untuk kehidupan yang berkeadilan dan demokratis, khususnya di Sulsel.
Tetapi di tengah upaya itu, LAPAR menemukan sejumlah realitas yang justeru tidak relevan dengan penumbuhan demokrasi yang kuat dan penciptaan pranata pluralitas yang manusiawi. Sejumlah indikasi dapat menjelaskan semua itu.
Pertama, demokrasi. Pasca reformasi tahun 1998, di Sulsel panggung demokrasi didominasi elite lama-orang kuat lokal dengan jejaringnya.
Mereka adalah pihak-pihak yang sejak rezim Orde Baru memiliki akses yang kuat terhadap sumberdaya ekonomi, politik, dan sosial. Mereka pun memiliki jangkar kuat pada lapis birokrasi.
Melalui multi sumber daya itu, maka panggung-panggun demokrasi disesaki oleh mereka dan jejaringnya.
Menariknya, sebab dominasi itu diisi dengan logika demokrasi, bahkan instrumen-instrumen demokrasi juga dilaluinya.
Ketika otonomi daerah resmi diterapkan 2001 silam, kelompok itu pun tak ketinggalan menyuarakan desentralisasi.
Namun, desentralisasi yang diteriakkan targetnya untuk meluaskan ruang penguasaannya terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik.
Ketika otonomoni daerah diterapkan tahun 2001 silam, elite lokal yang berjangkar pada birokrasi berpacu memompa ekonomi lokal dalam bentuk PAD.
Argumentasinya, desentralisasi harus diapresiasi dengan kekuatan ekonomi lokal. Di sini, investasi di aras lokal dipompa sedemikian rupa.
Tanda-tanda liberalisasi ekonomi diranah lokal menampakkan wujudnya. Akibatnya, sumber-sumber penghidupan rakyat kadangkala menguap diambil alih investor atasnama pembangunan.
Akibat lain, rusaknya daya dukung lingkungan hidup akibat investasi yang massif itu harus dirasakan secara berjamaah dalam bentuk bencana.
Jelang pemilukada langsung diterapkan 2005 lampau, elit-elit lokal yang dimaksudkan tadi menyiapkan diri untuk terlibat sebagai kandidat kepala daerah.
Konsolidasi dan penguatan jaringan ekonomi-politik dilancarkan. Tak pelak, panggung demokrasi lokal semakin disesaki aktor-aktor yang terdiri dari elit lama dan jejaringnya yang sejak era Orde Baru memang berkiprah disejumlah ruang, terutama ekonomi, politik, dan pemerintahan.
Akibat semua itu, rakyat sebagai Demos menjadi tak berdaya tak berdaulat. Posisi mereka di aras demokrasi lokal tak lebih sebagai objek, atau angka-angka statistik yang bernyawa.
Kedua, pluralisme. Sulawesi Selatan boleh dikata adalah salah satu daerah yang kurang efektif mengelola pluralitas warganya. Dengan modal sosial beragam etnik, budaya dan agama provinsi ini sesungguhnya bisa menjadi kuat dalam membangun tata sosial-kemasyarakatan yang manusiawi. Namun, sayangnya, hal itu tak terfaktakan.
Setelah otonomi daerah tahun 2001 silam, kekacauan pluralitas semakin menjadi. Kebebasan berekspresi diapresiasi dengan memunculkan kehendak menerapkan syariat Islam sebagai regulasi lokal.
Ironisnya, aspirasi ini malah direspon positif oleh sejumlah kalangan dilevel parlamen, hingga eksekutif didaerah-daerah. Padahal, sebagaimana diketahui, dasar Republik ini adalah Pancasila dan UUD 1945.
Amatan LAPAR, fenomena ini adalah bentuk pertemuan kepentingan sejumlah pihak dengan kelompok masyarakat tertentu yang menginginkan Syariat Islam menjadi regulasi. Dengan kata lain, diresponnnya aspirasi itu dianggap sebagai asset politik untuk keperluan pilkada yang dijalankan 2005 lalu.
Dampaknya, politik identitas (Islam) tampil mendominasi ditengah pluralitas warga Sulsel. Kelompok warga minoritas sesekali menjadi penonton, dan bahkan seringkali diserang oleh kelompok agama tertentu tanpa penindakan secara hukum.
Menariknya, baik pluralisme maupun demokrasi senantiasa didengungkan oleh elit lokal kita, terutama yang duduk sebagai wakil rakyat maupun di eksekutif. Kedua isu itu senantiasa dibicarakan di forum-forum resmi.
Dengan situasi begitu, demokrasi sama sekali tak mampu membingkai pluralitas warga. Dan sebaliknya, pluralisme tak mampu diletakkan sebagai energi yang memperkuat demokrasi lokal didaerah ini.
Padahal, secara teoritis, pluralitas warga dapat memperkuat demokrasi, dan demokrasi dapat membingkai fakta pluralitas warga.
Oleh karena itu, sepanjang sejarahnya, LAPAR berkesimpulan bahwa sesungguhnya pluralisme dan demokratisasi di daerah ini hanya kuat di wacana, tetapi lemah dalam praktek nyata. Pada masa mendatang, hal ini sebaiknya diletakkan sebagai agenda pembangunan manusia di aras lokal.(*)
ABDUL KARIM
Dirktur Eksekutif LAPAR Sulsel
-
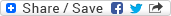
- Log in to post comments
- 152 reads