Otonomi dan Diskriminasi
Robert Endi Jaweng
Ikon konten premium Cetak | 19 Juni 2015
Terbitnya instruksi wali kota Banda Aceh belum lama ini, yang membatasi jam malam bagi perempuan berada di luar rumah, kembali "mengonfirmasi" soal serius dalam kehidupan publik kita.
Selain esensinya yang sulit dicerna nalar dan tak urgen dari sisi kebutuhan hukum setempat, kebijakan semacam ini selalu berulang muncul di bumi Tanah Rencong, seperti halnya pula terjadi di kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan lain-lain tempat, tanpa respons tegas dari pemerintah pusat.
Bias tafsir otonomi, di antara aneka faktor lain, tampaknya jadi sebab utama. Terlebih dalam konteks Aceh di mana berlaku status otonomi khusus dalam kadar yang melampaui skema desentralisasi asimetris yang lazim. Di sini, agenda setting tidak saja disusun untuk meresonansi kondisi spesifik dan keragaman lokal, juga menyiratkan aksentuasi yang tegas untuk berlainan dari daerah-daerah berotonomi biasa/jamak dan bahkan ingin berbeda dari kebijakan pusat. Dalam orientasi dan bobot setara, munculnya perda bernuansa agama, regulasi pengaturan perilaku dan tata busana, hingga pilih kasih politik alokasi fiskal mencerminkan upaya restriksi ke dalam (internal daerah) dan diferensiasi ke luar sebagai penegasan identitas pembeda dari daerah-daerah lain.
Ambiguitas pemda
Desentralisasi/otonomi di Indonesia memang didesain sebagai kerangka administratif guna mewadahi pengaturan-pengelolaan keragaman lokal. Otonomi menjadi struktur kesempatan baru bagi munculnya narasi dan ekspresi lokal yang pernah lama tiarap atau tersembunyi di bawah karpet kekuasaan otokrasi-sentralistik sebelumnya. Bahkan, dalam praktiknya yang eksesif, otonomi tak jarang bagai kotak pandora: berhamburannya identitas-identitas lokal secara arbitrer yang dalam interrelasinya melibatkan kontestasi tak bebas nilai dan hasrat saling mengalahkan.
Pada perkembangan lanjut, atas nama otonomi, daerah tampak begitu getol menegaskan perbedaannya secara eksternal dari daerah lain atau dengan pakem kebijakan nasional, tetapi cenderung lemah atau abai merekognisi keragaman internal daerah itu sendiri sebagai entitas lokal yang hakikatnya memang tak tunggal. Ambiguitas demikian membuat pemda sulit bersikap asertif atas munculnya upaya dominasi hingga kriminalisasi oleh suatu kekuatan sosial di aras masyarakat. Tidak saja membiarkan (crime by omission), pemda justru turut menyulut (crime by commission) munculnya konflik komunal yang berkelindan dengan praktik eksploitasi/politisasi identitas.
Celakanya, ambiguitas itu bergerak jauh merasuk ruang formil negara-lewat regulasi atau instrumen fiskal-yang melembagakan praktik diskriminasi dalam aras kebijakan resmi pemerintah. Otonomi tidak dikerjakan dalam mandat sejatinya untuk mengafirmasi lapisan sosial seperti kaum marjinal, minoritas, perempuan, dan anak yang memerlukan keberpihakan dan hadirnya negara.
Alih-alih, jamak terjadi justru otonomi itu dipakai pemda untuk memproteksi dan memfavoritkan mayoritas dan kelompok kuat yang sebenarnya tak perlu "dibela" khusus/berlebihan untuk bisa meraih akses ke keadilan, proteksi, dan seterusnya. Absennya afirmasi di satu sisi dan menonjolnya favoritisme pada sisi lain membuat raut otonomi kita tampak sangar, mencemaskan, menghadirkan lingkungan persoalan baru bagi kelompok warga rentan. Praktik pelembagaan diskriminasi ini jelas menggerus otonomi sebagai ruang baru bagi hidup bersama dan peluang mengusahakan kebaikan umum.
Dalam pengerjaannya, diskriminasi dilembagakan lewat manipulasi kelemahan demokrasi prosedural yang digiring sebagai demokrasi numerik dan politik legislasi menang-menangan. Logika penyusunan kebijakan dilakukan berdasarkan hitungan numerik mayoritas, padahal sejatinya suara terbanyak itu menjadi berbahaya ketika urusannya sudah berkaitan dengan kepentingan minoritas dalam kerangka kepentingan kolektif warga. Inilah sindrom desentralisasi tanpa nation-menyitir Mochtar Pabottingi-yakni suatu purwarupa otonomi yang gersang imajinasi kebangsaan, meski kita hidup dalam satu teritori negara, bahkan daerah yang sama. Otonomi berpotensi gagal dalam membangun hubungan kongruen antara sikap kedaerahan dan keindonesiaan, membuat daerah sebagai ruang hidup bersama justru terasa menyesakkan secara sosial.
Malafungsi otonomi tersebut berkelindan dengan penyakit akut dalam sektor publik kita yang masih kuat mewarisi mental model dan kultur birokrasi kolonial. Dalam kasus Aceh, kebijakan dibuat bukan untuk mengatur tanggung jawab pemda menjamin keamanan warga (memastikan petugas satpol PP ada di tiap titik rawan, misalnya), tetapi justru membatasi perilaku warga. Hak dasar warga untuk bergerak tanpa batasan waktu dan tempat guna mencari sumber penghidupan terpaksa tunduk di depan tabiat birokrasi yang malas menunaikan tugas wajibnya, atau bahkan hanya pencitraan politik atau menyalin perhatian warga dari kinerja buruk pemda kepada pesona daerah agamais, pemimpin religius, dan seterusnya. Stereotip "perempuan keluar malam" dan karakter diskriminasi (bahkan terhadap laki-laki sumber ancaman) juga inheren dalam alam pikir kebijakan itu, alih-alih mengambil tindakan afirmasi kalau memang benar keamanan perempuan sungguh rentan dalam kondisi rawan saat ini.
Pusat hadir
Pelembagaan diskriminasi, beserta segala kerusakan fatal yang timbul, adalah problem pada aras kebijakan, dan pelakunya negara itu sendiri. Sebaran kasus (beresensi sama, beragam modus) yang terjadi di ratusan daerah saat ini menjadi bukti nyata bahwa skala masalahnya adalah nasional. Semua itu bermuara pada satu imperasi: pemerintah pusat harus memberi respons jelas! Bahkan jika diskriminasi itu bernuansa (apalagi bersubstansi) agama, urusannya tentu bukan lagi soal otonomi, meski jika otonomi itu ditafsir secara sangat lentur seperti hidden-autonomy, tetapi sudah merupakan sebentuk subversi kebijakan atas otoritas pusat yang-menurut UU No 22/1999 hingga UU No 23/2014-berwenang mutlak dalam urusan agama.
Adakah bukti, setidaknya sinyal, yang mengarah ke sana? Tidak! Pusat hanya berlagak hadir, lewat respons normatif di pemberitaan media. Instrumen otoritatif berupa pembatalan kebijakan dan pengenaan sanksi administrasi atas kepala daerah hanya terkesan garang ketika dinormakan dalam beleid otonomi.
Kecuali ribuan perda pajak, retribusi, dan investasi, hingga hari ini belum satu pun kebijakan lokal yang melembagakan diskriminasi dibatalkan. Tidak ada terapi kejut bagi daerah bersangkutan, serentak mencegah efek tular ke daerah lain guna menirunya lantaran politik pembiaran pusat. Mantra Nawacita "menghadirkan kembali negara", "menolak negara lemah", "restorasi sosial guna memperteguh kebinekaan", entah apa lagi, hari ini diuji secara nyata untuk membuktikan tuahnya. Aceh, juga 150 daerah lain, menjadi ajang pembuktian. Mari kita tunggu!
Robert Endi JawengDirektur Eksekutif KPPOD, Jakarta
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/06/19/Otonomi-dan-Diskriminasi
-
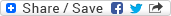
- Log in to post comments
- 649 reads